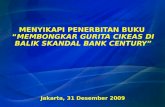PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM KERANGKA GOOD …...pada 1970-an sebagai akibat skandal korporasi...
Transcript of PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM KERANGKA GOOD …...pada 1970-an sebagai akibat skandal korporasi...

_____________________
* Sugiyanto, STPMD “APMD” Yogyakarta and A Student of Doctoral Program, Tjahjono,
H.K., Dept. of Management Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Hartono, A., Dept. of
Management Universitas Islam Indonesia; Khuluq, L., Universitas Islam Negeri
Sunankalijaga Yogyakarta
corresponding author: [email protected]
[email protected] ; [email protected] ; [email protected]
PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM KERANGKA GOOD
CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA KESEJAHTERAN SOSIAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sugiyanto1, Heru Kurnianto Tjahjono
2, Arief Hartono
3, Lathiful Khuluq
4
ABSTRACT: Penelitian responsibitas dalam kerangkan good corporate governance bertujuan
untuk mengetahui prinsip responsibilitas dalam kerangka good corporate governance dan
model governance lembaga kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tipe
penelenitian bersifat studi kasus.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah diskriptif kualitatf, yaitu peneliti memberikan gambaran
mengenai prinsip responsibilitas dalam kerangka good corporate governance lembaga
kesejahteraan sosial di DIY. Hasil penelitian menunjukan ada lima prinsip responsibilitas yang
terjadi pada lembaga kesejahteraan sosial di DIY dan ada lima model governce lembaga
kesejahteraan sosial di DIY.
Walapun penelitian dilakukan selama 8 tahun, penelitian ini masih ada kelemahan, maka
disarankan penelitian lanjutan menganalisis hubungan antar indicator good corporate
governance. Implikasi penelitian menjadi bahan refleksi bagi pengambil kebijakan, pengelola
LKS dan para donatur.
Key Words: Prinsip Responsibilitas, Good Corporate Governance, Lembaga Kesejahteraan
Sosial.
PENDAHULUAN
Cadbury (1992) memberikan pengertian corporate governance yaitu
keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial serta tujuan individu dan tujuan
komunitas. Di samping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan segala
sumber daya yang memperhatikan seluruh kepentingan, baik individu, organisasi dan
masyarakat.
Kedudukan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Indonesia secara hukum
diatur oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, dan secara operasional LKS diatur oleh
Kementrian Sosial RI. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011-2017, sampai
penelitan ini berakhir Kementrian Sosial Republik Indonesia (RI) belum mengatur
good corporate governance LKS. Untuk mendalami prinsip responsibilitas good
corporate governance LKS peneliti mengadop Surat Keputusan Menteri BUMN No.
Kep-117 / M-MBU / 2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Good Corporate

2
Governance (GCG) pada BUMN. Corporate Governance adalah suatu prosedur
struktur yang digunakan oleh organ organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini menekankan pada keberhasilan
usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka
panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai moral para stakeholder.
moral hazard.
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dimaksud di sini merupakan organisasi
sosial seperti tersirat dalam Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Organisasi sosial seperti dimaksud pada Undang-Undang No.11
Tahun 2009 tersebut mengandung makna spesifik kesejahteraan sosial sehingga lebih
merupakan istilah teknis. Pengertian demikian berbeda dengan makna “organisasi
sosial” dalam arti umum, seperti digunakan dalam ilmu sosiologi dan ilmu lainnya.
Mengapa penelitian ini memilih lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY)?, karena di DIY memiliki 366 LKS (Dinas Sosial DIY 2015), LKS DIY sebagai
barometer LKS secara nasional, LKS di DIY dari tahun 2010-2017 selalu mendapat
penghargaan dari Pemerintah sebagai LKS berprestasi tingkat nasional, lebih dari 25%
LKS di DIY lahir sebelum Indonesia Merdeka 1945 dan angka kesenjangan atau gini
rasio kota Yogyakarta 4.2% dan nasional 3.94%. Tim monitoring standar nasional
pengasuhan anak (SNPA) menemukan data tentang LKS di DIY bahwa manajemen
cenderung bersifat tradisional dan tertutup: (a) SDM belum profesional dan lebih
banyak didominasi relawan daripada pegawai LKS, (b) jabatan rangkap: ada pengurus
merangkap jabatan, (c) nepotisme: pendiri memaksakan anggota keluarga dan pejabat
publik serta teman dicantumkan dalam struktur organisasi LKS.
KAJIAN TEORI
Responsibilitas, artinya para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban
atas semua tindakan dalam mengelola organisasi kepada para pemangku kepentingan
(Pierre and Peters, 2000). Unsur pengelola pada LKS terdiri dari dari.
Apabila LKS dilihat melalui pendekatan teori, LKS grand teorinya berada
pada ranah organisasi. Dalam hal ini, Taylor (1967) berpendapat bahwa organisasi
merupakan suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan
untuk mengejar tujuan bersama, dan Voos (1976), menyatakan bahwa organisasi
adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah
batasan yang relatif dapat diidentifikasi, dan bekerja atas dasar relatif secara terus-
menerus untuk mencapai tujuan bersama.

3
Organisasi nonprofit seperti organisasi sosial, NGO, dan LSM di Indonesia
melalui pendekatan hukum ada dua yang menaungi organisasi nonprofit, yaitu yayasan
dan badan sosial. LKS dalam hal ini merupakan salah satu bentuk badan sosial bersifat
formal dan fungsi utamanya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang
bertujuan memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat, pernyataan
tersebut sesuai hasil studi Zulkhibri (2014), Dalam kaitan ini, LKS berperan sebagai
mediator antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat, khususnya
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepentingan stakeholder lain
yang terkait.
Mengadop pendapat Chonyngton (1910) LKS sebagai organisasi formal
memiliki unsure: pendiri, pembina, pengawas, pengurus, pengelola, pemegang saham
(pasar filantropi), dan klien. Berpijak pada keberadaan unsur-unsur tersebut dalam
sebuah organisasi, standar kerja LKS bukan pada efisiensi, melainkan lebih pada
efektifitas yang mengandalkan tenaga profesi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan
sosial dan relawan sosial. Farahmand (2011) menegaskan ketiga sumber daya manusia
ini pun bukanlah merupakan sebuah teknologi hardware, melainkan humanware.
Keuntungan yang didapatkan pun bukan berupa materi dan tidak dibagikan kepada
pemegang saham, melainkan keuntungan berwujud “trust” dan dikembangkan untuk
peningkatan dan perluasan pelayanan kepada klien.
Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB 1980), menjelaskan
bahwa jenis donor pada organisasi nonprofit ada dua, yaitu institusi dan individu.
Kelompok pertama dapat terdiri dari beberapa macam, misalnya LSM, instansi
pemerintah, lembaga derma/filantropi, badan internasional, atau lembaga-lembaga
keuangan, serta bank; semua institusi ini dapat berupa, institusi lokal maupun institusi
asing. Kelompok kedua adalah donor individual, yakni perseorangan dapat berasal dari
masyarakat atau usaha komersial dan lokal maupun asing.
Penjelasan di atas menunjukan bahwa organisasi nir laba salah satu fungsinya
menghimpun donatur dari public dan menyalurkan kepada klien, maka public layak
untuk mengetahui tatakelola kususnya resposibilitas dan transparansi dalam mengelola
donatur tersebut.
Sejarah Good Corporate Governance
Istilah corporate governance pertama sekali digunakan di Amirika Serikat
pada 1970-an sebagai akibat skandal korporasi dengan kegiatan politik yang tidak
sehat (Cadbury, 1992). Struktur corporate governance merupakan suatu korporasi
dipengaruhi oleh faktor korporasi yang dianut budaya, dan sistem hukum yang berlaku
sehingga aplikasinya di setiap perusahaan dan negara berbeda (Antonella, 2001).
Dalam hal tersebut, Antonius dan Subarto (2004) berpendapat bahwa corporate
governance diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan

4
yang efektif dan bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem, nilai, proses bisnis,
kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan mendorong pertumbuhan kinerja
perusahaan, pengelolaaan sumberdaya dan risiko yang efisien dan efektif, serta
pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lain.
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, merumuskan good governance
sebagai “pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat”. Dengan
demikian Corporate governance akan membatasi dan mengatur perilaku pribadi dalam
sistem agar budaya serakah yang menggambarkan pertarungan kebebasan pribadi dan
tanggungjawab kolektif tidak terjadi, sebab dalam organisasi apapun konflik
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama akan selalu muncul dan saling
mendahului. Akibatnya, antara pemilik dan agen saling hidden information (Berle
and Means, 1932).
Tatakelola organisasi merupakan subyek sangat penting, awalnya diterapkan
pada perusahaan berkembang pada tatapemerintahan dan selanjutnya mengalir di
semua organisasi, termasuk organisasi nonprofit. Oleh karena itu, organisasi nonprofit
juga dituntut menjadi organisasi profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good
corporate governance (Dwi Sektiono, 2016). Mengingat bahwa di dalam organisasi
nonprofit dapat timbul sebuah fenomena sehingga hal ini semakin menguatkan
tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi secara keseluruhan. Tuntutan
tersebut terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi
dalam upaya pemenuhan hak-hak publik.
Alinjoyo dan Zaini (2004) memformulasikan dimensi tatakelola yang baik
terdiri dari transparansi, akuntabiltas, responsibility, independence, fairness (kewajaran
dan kesetaraan). Dimensi ini digambarkan dalam wujud keadilan dan kesetaraan dalam
memenuhi hak-hak shareholder dan stakeholder berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan hal demikian juga dapat diterima atau berlaku
pada tatakelola LKS. Situasi ini juga sesuai dengan teori stakeholder yang diajukan
Mason dan Mahoney (2008); Charron (2007); dan Kooskora (2008). Organisasi yang
baik dan ideal, pastilah dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan digunakan asas-asas
good governance tersebut. Asas-asas ini dipakai untuk menjaga agar tindakan
organisasi sesuai dengan tujuan dan tindakan yang diambil tidak menyengsarakan
anggota organisasi yang dilayaninya.
Good Corporate Governance LKS
Corporate governance lembaga kesejahteraan sosial adalah seluruh upaya
untuk memelihara keseimbangan, keikhlasan, kejujuran, tanggungjawab, dan
kehormatan seluruh stakeholder dilakukan dengan cara membangun sistem nilai untuk

5
mewujudkan keadilan melalui peraturan formal dan informal serta modal kerelaan
pasar filantropi sebagai nilai moral untuk kepentingan terbaik bagi penerima manfaat
secara kaaffah (Sugiyanto 2018).
Secara nasional payung hukum tertinggi yang mengatur tentang LKS di
Indonesia sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 ini masih
memiliki kelemahan, sehingga pemerintah berusaha melengkapi untuk memperkuat
undang-undang tersebut dengan: 1) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 184 tahun 2011
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 2) Peraturan Menteri Sosial RI nomor
17 tahun 2012 tentang Akriditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, 3) Peraturan
Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan
4) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Nasional
Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dari kelima peraturan hukum tersebut teryata belum
mengatur tentang perangkat organisasi LKS yang fokus pada tatakelola LKS, sebagai
contoh perlindungan bagi LKS yang tidak berbadan hukum, dan tipologi yang disusun
bukanlah untuk mengatur tatakelola, melainkan tipologi untuk memenuhi persyaratan
fisik dan nonfisik keberdaan LKS. Sehingga sampai saat ini masih memiliki celah
kelemahan, sebab di dalamnya belum terdapat aturan tentang tatakelola (pemerintahan
LKS). Situasi serta kondisi seperti itu diduga sengaja diserahkan pemerintah
sepenuhnya kepada pihak masyarakat, mengingat isi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan lain yang menyertainya
tidaklah tersirat. Berdasarkan atas hal ini, sudah seharusnya pada AD-ART setiap LKS
tersirat mengenai batas kekuasaan pendiri, hubungan pendiri dengan pengelola,
mekanisme hubungan pengelola dengan penerima manfaat, hubungan pendiri dengan
penerima manfaat, dan hal-hal lain yang diperlukan LKS.
Perihal mekanisme implementasi kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh
pendiri, model eksekusi LKS dilaksanakan oleh pengurus yang berperan sebagai
pemegang kuasa dalam operasional, hal ini diperlukan mekanisme
pertanggungjawaban pengurus kepada pemegang kekuasan tertinggi. Mengenai
mekanisme pertanggungjawaban perangkat organisasi mulai dari pendiri, pengawas,
pembina pengelola, pegawai, para profesional dan klien sampai dengan posisi
kedudukan, serta kewenangan masing-masing LKS yang diperkirakan sangat beragam
bentuk dan sistemnya. Di samping itu, dipentingkan pula penjelasan mengenai
wewenang dan kuasa, karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki organ LKS
merupakan material untuk mengukur kinerja LKS, dan akhirnya dapat diformulasikan
untuk mengetahui hubungan keterikatan serta sehat tidaknya LKS tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas tentang payung hukum LKS yang belum
mengatur tatakelola LKS maka berdasarkan studi empiris peneliti ditemukan bahwa
para pengiat LKS dalam praktek tatakelola di organisasinya meminjam payung hukum

6
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Kebijakan pengiat LKS
mengunakan payung hukum undang-undang yayasan dilegalkan oleh pemerintah,
dalam hal ini semua akte pendirian LKS yang dibuat dan disyahkan oleh pihak yang
berwenang dalam bentuk yayasan dan atau badan sosial.
Dengan demikian payung hukum LKS sampai saat ini menjadi ganda antara
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-
Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Dengan payung hukum ganda
dan masih dilengkapi dengan peraturan hukum lain yang menyertainya diduga praktek
tatakelola dimasing-masing LKS akan mengalami perbedaan dan keunikan. Perbedaan
dan keunikan tatakelola setiap LKS layak dicuragai secara positif untuk mengkaji lebih
dalam untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang organisasi non profit dan
secara praksis dapat diterapkan para pengiat LKS dalam menjalankan roda organisasi
tersebut.
Penelitian ini menelusuri melalui pemeran kunci LKS dengan panduan
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional LKS atau
ada faktor lain yang menciptakan LKS tersebut menjadi baik. Berdasarkan pada uraian
tersebut di atas, pemeran kunci tatakelola organisasi nirlaba ”LKS” terdiri dari pendiri,
pembina, pengawas, pengurus yayasan dan pengelola, serta pihak eksternal yang terdiri
dari pemerintah cq Dinas Sosial, badan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial
(BK3S), lembaga kegiatan keseahteraan sosial (LKKS) dan donatur. Sedangkan forum
tertinggi pada LKS ada dua jenis, pertama berkaitan dengan manjemen LKS, yakni
pada rapat pleno tahunan (RPT); dan kedua berkaitan dengan pelayanan klien terletak
pada case conference.
Inti dari konsep good governance adalah mekanisme relasi antar kelompok dan
struktur kekuasaan pada proses membuat kebijakan. Kelompok dalam hal ini adalah
kelompok pengurus dan kelompok pengelola (agen). Central pedoman berperilaku
pengelola dan pengurus adalah tata nilai kesepakatan yang dituangkan dalam anggaran
dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi yang telah disyahkan oleh
notaris. Ada enam kemungkinan interaksi dan relasi yang terjadi pada LKS antara lain
:
1. Pengelola (Pl) sebagai aktor utama berelasi tinggi (Rt) terhadap stakeholder (S).
2. Pengelola (Pl) sebagai aktor utama berelasi rendah (Rr) terhadap stakeholder (S)
3. Pengurus (Pr) sebagai aktor utama berelasi tinggi (Rt) terhadap stakeholder (S)
4. Pengurus (Pr) sebagai aktor utama berelasi rendah (Rr) terhadap stakeholder (S)
5. Pengelola (Pl) dan Pengurus (Pr) sebagai aktor utama berelasi tinggi (Rt) terhadap
stakeholder (S)
6. Pengelola (Pl) dan Pengurus (Pr) sebagai aktor utama berelasi rendah (Rr) terhadap
stakeholder (S)

7
Untuk mengetahui praktek responsibilitas good corporate governance LKS,
maka dirumuskan pedoman sebagai berikut :
1. Responsibilitas sangat baik (SB) dibuktikan dengan interaksi dan relasi “melebihi”
dari tata nilai dalam AD-ART dan peraturan lain yang disyahkan.
2. Responsibilitas baik (B) dibuktikan dengan interaksi dan relasi sesuai dengan tata
nilai dalam AD-ART dan peraturan lain yang disyahkan.
3. Responsibilitas cukup baik (CB) dibuktikan dengan interaksi dan relasi tidak sesuai
dengan tata nilai dalam AD-ART dan peraturan lain yang disyahkan.
4. Responsibilitas kurang baik (KB) dibuktikan dengan interaksi dan relasi
menyimpang dari tata nilai dalam AD-ART dan peraturan lain yang disyahkan.
METODE PENELITIAN
Studi prinsip responsibilitas dalam kerangka good corporate governance LKS
di DIY dilakukan melalui studi literature dan focus group diskusi kelompok supra LKS
dilanjutkan pengujian dilapangan melalui case studi. Studi literature pada jurnal-jurnal
internasional seperti Journal of Healthcare Management, VOLUNTAS: International
Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations., International Journal of Law and
Management, Journal of Knowledge Management University of Alabama, USA,
International Journal of Social welfare, dll.
Selanjutnya diskusi melibatkan 8 personal sebagai tim di Dinas Sosial DIY,
profesi anggota tim terdiri dari peneliti bidang manajemen dan bidang sosial, praktiksi
NGO, Dinas Sosial, Balai Besar Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI
Region III, Akademisi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diskusi membahas responsibilitas
good corporate governance pada lembaga kesejahteraan sosial di daerah DIY.
Action research dilakukan melalui analisis hasil sensus LKS tahun 2015,
borang akriditasi LKS dan kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas
Sosial dan berbagai pelatihan penguatan kapasitas LKS yang diselenggarakan BK3S
DIY.
HASIL DISKUSI
LKS berfungsi untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan
kesejahteraaan sosial individu, kelompok dan masyarakat melalui pemahaman,
pembentukan atau mengubah atribut. Karakteristik LKS berbasis amal,
mempekerjakan pekerja sosial, relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial,
sumberdaya berpusat pada pasar filantropi yang tidak mengharapkan keuntungan.
Hasil produksi organisasi berwujud jasa dalam bentuk “nilai moral”, dan sumberdaya

8
utama organisasi nirlaba adalah manusia sebagai aset yang paling berharga sebab
prinsip kerja organisasi nirlaba adalah “dari-oleh-untuk manusia”.
Bibiografi LKS di DIY
Sejarah berdirinya LKS di DIY bersifat bottom up, artinya LKS didominasi
oleh individu dan keluarga dengan semangat filantropi dan charity. Kondisi ini
disebabkan banyak warga di daerah Yogyakarta dalam keadaan: miskin, terlantar,
disabilitas, tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Sukaryadi, 2014). Dampak dari kondisi
tersebut, governance LKS menjadi bervariasi sesuai dengan kemampuan kapasitas
sumberdaya keluarga, tetapi juga tidak menutup kemungkinan melahirkan berbagai
permasalahan, baik masalah dari internal LKS maupun masalah eksternal LKS.
Sebaran hasil sensus LKS DIY Tahun 2015 tabel 1. berikut.
Tabel 1. Data LKS di Daerah DIY Tahun 2015
No. Dinas Sosial Kabupaten/Kota Jumlah
LKS
Tipologi
A B C D E
1 Kota Yogyakarta 68 - 10 31 24 3
2 Kabupaten Bantul 85 - 21 38 18 8
3 Kabupaten Kulonprogo 47 - 3 25 15 4
4 Kabupaten Gunungkidul 51 - 1 31 19 -
5 Kabupaten Sleman 115 2 29 44 16 24
Jumlah 366 2 64 169 92 39
Sumber: Laporan Tim Verifikasi LKS tahun 2015.
Keterangan Tabel 1. Data LKS di Daerah DIY Tahun 2015; Tipologi A:
mandiri; B: berkembang; C: tumbuh; D: embrio; dan E: bermasalah.
Tabel 1. di atas menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial cukup tinggi. Keberadaan dan peran LKS
sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan data LKS tersebut merupakan aset

9
serta peluang bagi pemerintah untuk mengentaskan berbagai permasalahan sosial yang
ada.
Bertolak dari uraian di atas, pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik
Indonesia berupaya mendorong peningkatan kualitas LKS melalui berbagai regulasi
agar mutu tatakelola LKS bertambah baik sehingga dapat mencapai program kegiatan
LKS yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Karena, tatakelola yang baik sangatlah
dibutuhkan sehingga LKS mampu bergerak pada arah yang ideal.
Berbicara mengenai pendanaan, LKS belum memiliki kemandirian dana dan
masih bergantung pada bantuan pasar filantropi serta bantuan negara. Dengan begitu,
pendanaan anggaran operasional LKS mengandalkan donasi. Akan tetapi, adanya
pengurus LKS yang berbasis keluarga dan SDM yang terbatas menyebabkan pihak
eksternal mengalami kesulitan melakukan pengawasan; situasi seperti ini layak
dicurigai akan terjadi kecurangan, tidak transparan, sistem akuntabilitas yang dibangun
menimbulkan rawan konflik, dan terjadi moral hazard yang merugikan berbagai pihak
karena hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Akhirnya, kepercayaan
publik terhadap LKS berkurang (lihat tabel1.); seperti ditunjukkan Data LKS di Daerah
DIY pada tabel tersebut, bahwa LKS tipologi E berjumlah 39, artinya LKS dalam
kondisi bermasalah dan sudah seharus secara serius mendapatkan perhatian
pemerintah.
Atas dasar itu, baik berbagai elemen yang terorganisasi dalam LKS maupun
secara perseorangan berkeinginan membantu pemerintah sesuai dengan kemampuan
dan pengetahuan masing-masing. Dalam kaitan ini, para pemilik LKS cenderung
beranggapan bahwa LKS bersifat universal sehingga kurang disadari bahwa kehadiran
LKS diatur oleh negara; seperti perizinan, standarisasi fasilitas, standarisasi SDM,
pengelompokan sasaran layanan, serta akreditasi lembaga dan pemberian penghargaan
melalui kegiatan pemilihan LKS berprestasi.
Model Governance LKS
Dari 366 LKS setelah diteliti terdapat lima model governance, model tipologi
tidak berpasangan (misalnya tipologi mandiri model governance birokrasi), tetapi dari
setiap model ada kemungkinan menyebar diberbagai tipologi. Kelima model tersebut
dijelaskan sebagaiberikut:
1. Model governance demokrasi
Model governance demokrasi ada 31% LKS. Model ini ditemukan pada KLS
pusat dan LKS yang berbasis universal. LKS pusat adalah LKS yang sengaja tidak
membuka cabang, dan jika membuka semua konsep, aturan dan kebijakan ada di
pusat cabang tinggal pelaksanakan. Untuk LKS bersifat universal yang masuk

10
dalam kotegogori governance birokrasi dicirikan dengan LKS-LKS yang tatakelola
sudah mapan, SDMnya professional dan stakeholdersnya berfungsi secara
maksimal.
2. Model governance otoriter
Model governance otoriter ada 9% LKS. Model ini ditemukan pada LKS berbasis
agama. Kususnya berbasis agama islam dan awalnya dikembangkan dari pondok
pesantren. Para staf dan relawan seolah-olah sebagai obyek yang harus bekerja dan
konsep serta kebiakan berada pada pimpinan. Governance otoriter kebanyakan
pengurus rangkap jabatan, dan cenderung semua keputusan ada pada abatan
puncak. Jabatan puncak ada pada pendiri atau organ yayasan.
3. Model governance birokrasi.
Model governance birokrasi ada 33% LKS. Model ini temukan pada LKS-LKS
yang telah memiliki unit produksi yang kuat, sehingga dana operasional untuk
pelayanan klien tidak mengantungkan dari donatur ansih, contoh LKS Mardi Wuto,
LKS Anur Serimpi dan LKS-LKS cabang yang keberadaannnya diatur oleh pusat,
seperti LKS Rumah Yatim, PKPU, Santa Maria dan Rumah zakat.
4. Model governance laissez faire.
Model governance laissez faire ada 10.8% LKS. Model ini ditemukan pada LKS-
LKS yang anggaran dasarnya belum kuat dan belum dibuat secara bersama antar
stakeholder. AD-ART ada cenderung dibuat sebagai persyaratan administrative
belum sebagai landasan kerja, sebagai contoh LKS yang mengabungkan
aktivitasnya antara lembaga pengasuhan anak dengan pondok pesantren dan pada
LKS-LKS yang sifatnya masih baru atau embrio dan sebagain LKS sedang
mengalami masalah, sehingga donaturpun sumbernya belum jelas dan tidak
diselektif. Jika ditemukan masalah model governance laissez faire seolah-olah di
dalam LKS ada shadow state (Hayden and Court, 2004). Model governace ini relasi
dan interaksi pemangku kepentingan tampak belum memiliki kebijakan program
startegis, sehingga setiap aktivitas sulit diklasifikasikan pada kegiatan preventif,
kuratif dan rehabilitative.
5. Model Governance pragmatis.
Model governace pragmatis ada 16.2% LKS. Model ini ditemukan pada LKS-LKS
yang jenis layananya universal, artinya LKS ini memiliki banyak layanan, sehingga
kliennya holistic missalnya satu LKS melayani lanjut usia, anak terlantar, KDRT,
dll. Model governance pragmatis tampaknya selalu memanfaatkan peluang yang
datang baik dari donatur pemerintah, masyarakat ataupun perusahaan. Model
governance pragmatis cenderung lemah pada konsep sehingga hanya
mementingkan kepraktisan, dibandingkan sisi manfaat, mementingkan hasil akhir

11
dari pada nilai-nilai yang dianut, kelemhannya kurang meperhatikan hukum yang
mengatur dan mengesampingkan keberlanjutan.
Berpijak pada teori corporate governance yang berkembang di Amerika dan
Eropa dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi potensi konflik pada organisasi
nirlaba ada tiga, pertama bentuk organisasi, kedua ukuran organisasi, dan ketiga
sumberdaya yang dimiliki organisasi. Apabila dilihat dari sumbernya, konflik
organisasi nirlaba ada dua macam: bersumber dari internal organisasi, dan bersumber
dari eksternal organisasi.
Konflik internal organisasi merupakan konflik antar stakeholders internal
(pendiri, pembina, pengawas, pengurus, staf/pelaksana, dan para profesional) karena
kepemilikan wewenang dan kekuasaan yang berbeda dalam pengambilan keputusan
dan pengunaan sumberdaya organisasi. Dalam kaitan ini, sumber konflik internal
organisasi nirlaba, terdiri atas 4 macam: a. Faksionalisasi kepentingan, pada
faksionalisasi dapat dilihat melalui beberapa hal, yakni sumber, motivasi, dan durasi.
Sumber faksionalisasi dapat terbentuk karena aspek historis, ideologis, dan pragmatis.,
b. Ketegangan antarlapisan kekuasaan dalam organisasi. Konflik dalam organisasi
nirlaba hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah bekerja di dalamnya. Bagi orang
yang berada di dalamnya, soal konflik merupakan bahan perbincangan sehari-hari;
dalam banyak kasus, soal konflik organisasi nirlaba jarang mengemuka kepada publik,
sering dipendam atau bahkan sengaja ditutupi demi kepentingan citra organisasi.
Sebagian stakeholders internal beranggapan bahwa konflik merupakan sebuah aib,
apabila organisasi yang mengusung nilai moral dalam bentuk nilai luhur dan misi
sosial terjadi konflik di dalamnya. Pada batas tertentu konflik ini merupakan salah satu
faktor penting sebagai penghambat organisasi nirlaba dalam mencapai tujuan
organisasi. Apabila terjadi ketegangan antara lapis pengawas dan pengurus, pengurus
dan para profesional, pengurus dan staf, staf dan para profesional akan terjadi konflik
sangat berbahaya; padahal, konflik jika didekati dengan cara berpikir positif akan
bermanfaat bagi organisasi nirlaba, yakni sebagai bahan dan media pembelajaran
terhadap masalah tatakelola, menjadi sarana bagi perbaikan kerja dunia organisasi
nirlaba, sebagai salah satu pilar demokrasi dan transformasi sosial., c. Tipologi
kepemimpinan, ada beberapa model tipe kepemimpinan dalam organisasi nirlaba,
yakni otoriter, demokratis, pragmatis dan dimensional atau situasional. Model
pemimpin ini juga tidak bebas konflik, sebab dapat mengakibatkan lemahnya
penegakan aturan dan kelambanan dalam pengambilan keputusan karena
mengutamakan proses., d. Subtansi gerak organisasi (sedikit banyaknya jenis layanan
yang diberikan kepada klien), artinya makin banyak jenis layanan yang diberikan
kepada klien/penerima manfaat maka semakin tinggi peluang konflik dan semakin
membatasi layanan sehingga peluang konflik juga akan mengecil.

12
Konflik eksternal organisasi merupakan tekanan dari faktor kebijakan dan
sumberdaya eksternal, utamanya adalah kebijakan donor dan keterbatasan sumberdaya.
Sebagai contoh kebijakan donor: dalam hal pengalihan donor dari negara asing kepada
negara yang dipandang tingkat kesejahteraannya lebih rendah daripada negara
Indonesia; kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan global dalam bentuk tuntutan
global kepada organisasi nirlaba (NGO-LKS) harus tunduk pada kebijakan MDGs, isu-
isu HAM, Global Compact, ISO, dan lain-lainnya.
Berdasarkan pada penjelasan di atas diduga akan timbul ketidakharmonisan di
antara pemeran organisasi nirlaba sehingga relasi antarpemeran organisasi nirlaba
tersebut perlu dibangun berdasarkan atas nilai moral, meliputi kejujuran, efisiensi,
kepercayaan, saling menghormati, dan kesetaraan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi
antara pendiri, penggagas, pengelola, staf, dan para profesional, serta pasar filantropi,
tetapi hal serupa juga dapat terjadi antara stakeholder internal dan stakeholder
eksternal, serta antara stakeholders internal dan penerima manfaat sehingga relasi yang
dibangun pada lembaga kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan upaya
mempertahankan keseimbangan antar berbagai pihak yang berkepentingan dan
berdampak pada tataran publik yang lebih luas.
Berdasarkan pada uraian tersebut, orientasi corporate governance yang utama
adalah memelihara keseimbangan antara hak seluruh stakeholders dan membangun
sistem nilai untuk mewujudkan nilai moral antar stakeholders. Hal sangat penting
dalam LKS tersebut berupa reputasi nilai moral, sebab tatkala lembaga dengan atribut
nilai moral baik, pasar filantropi akan terbetuk dengan sendirinya (Fadillah, 2011).
Dalam kaitan itu, sistem yang dibangun bertujuan menjaga kepentingan
seluruh stakeholder berkomitmen, mengembangkan, dan mengintegrasikan nilai moral
dengan peraturan formal dan peraturan nonformal secara efektif. Kedua pengaturan
tersebut bertujuan agar tidak timbul konflik antarsesama stakeholder.
Mengacu pada penjelasan ringkas di atas, dapat dirumuskan bahwa definisi
corporate governance versi lembaga kesejahteraan sosial bahwa, "seluruh upaya untuk
memelihara keseimbangan, keikhlasan, kejujuran, tanggungjawab, dan kehormatan
seluruh stakeholder dilakukan dengan cara membangun sistem nilai untuk
mewujudkan keadilan melalui peraturan formal dan informal serta modal kerelaan
pasar filantropi sebagai nilai moral untuk kepentingan terbaik bagi penerima manfaat
secara kaaffah".
Bentuk Responsibilitas
Tatakelola organisasi yang baik dan sehat dapat dideteksi dari penerapan
prinsip-prinsip good governance, kususnya transparansi dan akuntabilitas. Organ

13
pemegang kuasa organisasi ditangan BOD dan Pengelola. Maka para pengelola wajib
memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola organisasi
kepada para pemangku kepentingan.
Bila kita mengadop pada organisasi profit maka responsibilitas dimaknai
pertanggungjawaban perseroan baik kepada shareholders maupun stakeholder dengan
tidak merugikan kepentingan para shareholders maupun anggota masyarakat secara
luas. Dalam kontek ini di ditekankan dalam Undang- Undang perseroan haruslah
berpegang pada hukum yang berlaku atas 1). hak-hak pemegang saham., 2). perlakuan
yang adil terhadap seluruh pemegang saham., 3). peran stakeholder dalam corporate
governance., 4). kewajiban pengungkapan (disclosure) dan transparency., 5).
tanggungjawab direksi dan komisarit.
Secara eksplisit dan implisit ada indikasi bahwa teori corporate governance
tersebut di atas cenderung memakai pendekatan yang dilandasi dengan anggapan
"kecurigaan terhadap perilaku tidak bertanggungjawab pihak dalam" terhadap
kepentingan stakeholder (Sheffied dan White 2004). Hal tersebut dapat terjadi karena
sebagian besar alasan utama yang diajukan berkaitan dengan adanya pemisahan antara
manajemen dan pemilik sehingga meningkatkan masalah agensi. Upaya mengatasi hal
tersebut dilakukan dengan: mekanisme pasar, nilai sosial dan lingkungan, peraturan
dan supervisi yang efektif, integritas dan efisiensi penegakan hukum, struktur
kepemilikan serta kekuasaan politik yang dapat melakukan kinerjanya secara efektif
(La Porta et al, 1999).
Berkaitan dengan hal tersebut, John (1977) berpendapat bahwa permasalahan
lembaga nirlaba lebih kompleks sebab dalam organisasi bisnis yang mempunyai
keuntungan berwujud materi atau uang adalah pemegang saham, sedangkan pada
organisasi nirlaba yang mempunyai keuntungan adalah stakeholders, “pemilik moral”,
dan penerima manfaat memiliki keuntungan berwujud “reputasi nilai moral”. Terlebih
pada lembaga kesejahteraan sosial, permasalahan akan makin kompleks karena
semakin beragam yang dilayani dengan varian berjumlah 26 penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS). Mengingat aktivitas utama bahwa situasi apapun harus
satu suara dalam tujuan, karakter, dan arah sehingga tujuan organisasi itu dibentuk
untuk menghasilkan dan menyukseskan organisasi. Hal ini dilakukan karena
reputasinya sering berubah, dan di sisi lain pengoperasionalan lembaga mengandalkan
"pasar filantropi”.
Hal tersebut berkaitan dengan asumsi bahwa posisi stakeholders, khususnya
pengelola (agen) ditentukan oleh nilai moral sebagai budaya perusahaan (corporate
caltur) sehingga harus dapat menjadi aspirasi paling inovatif. Dengan cara sama
menghormati pula nilai pribadi dan nilai umum, serta mematuhi nilai secara konsisten
dalam semua aspek operasional. Karena, sesuatu yang mendasar adalah bahwa “nilai

14
akan berbicara”, baik di seluruh area stakeholders maupun bagi penerima mafaat dan
publik yang tidak terbatas.
Atas dasar itu, stakeholders internal (dewan pengawas, pengurus, staf, dan
para profesional) di dalam organisasi nirlaba harus memahami pasar filantropi,
penerima manfaat dalam bingkai satu suara, satu langkah, dan satu hati. Dengan
demikian, tuntutan yang tersirat adalah harus mengerti, bertanggungjawab dan
melaksanakan tupoksi masing-masing; apabila salah atau lemah, overlod dan over
acting dalam menjalakan tupoksinya akan terbuka peluang terjadi konflik kepentingan
antar stakeholders internal (dewan pengawas, pengurus, staf, dan para profesional).
Landasan sistem nilai corporate governance LKS
Sumberdaya manusia LKS sebagian besar terdiri dari kumpulan para relawan.
Oleh karena itu, LKS berupaya melindungi kepentingan seluruh stakeholder dan
penerima manfaat secara seimbang dengan landasan yang sangat kuat sebagai sistem
nilai, yakni nilai moral berbasis ikatan hati.
Akan tetapi, perlu menjadi pertanyaan pula bahwa upaya kesungguhan LKS
untuk melakukan implementasi sistem nilai tersebut tanpa harus banyak syarat dan
bersiasat secara bertanggungjawab. Karena, implementasi sistem nilai sebenarnya
sebuah kewajiban bersifat personal dan memiliki konsekuensi besar serta mengikat
segenap individu yang melakukan interaksi dengan apa adanya dalam membangun
relasi tersebut. Apabila hal ini tidak diimplementasikan, secara nilai moral
membuktikan bahwa kumpulan para relawan itu termasuk bukan kelompok (seorang)
relawan (Meth. Kusumahadi, 2011).
Mekanisme interaksi yang tejadi pada LKS memiliki relevansi tinggi dengan
landasan nilai moral tersebut, khususnya berkaitan dengan skema kenyakinan,
keikhlasan, dan kekuasaan yang mengunakan pembiayaan pasar filantropi dengan
menggunakan prinsip terbaik bagi penerima manfaat. Pembiayaan tersebut
memberikan kepercayaan penuh kepada pasar filantropi atau donasi yang tidak pernah
meminta hak dari keuntungan atau bagi hasil. Keuntungan dari pasar filantropi oleh
pengelola digunakan untuk kegiatan produktif dengan hasil akhir berwujud reputasi
nilai moral, dan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing stakeholders
tergantung dari akad keikhlasan yang disepakati saat kontrak personal dengan lembaga
tersebut. Akad keikhlasan diikat oleh ikatan hati, bukan ikatan materi sehingga pamrih
materi sama sekali tidak tampak atau dengan lain perkataan tidak ada. Sistem nilai
yang memiliki dimensi moral berkaitan dengan perlunya disiplin diri sebagai konsep
moral dalam layanan kesejahteraan sosial, seperti tercantum di dalam moral spiritual
masing-masing stakeholders, antara lain kerja amal dan kerja filantropi dengan prinsip
kenyakinan (belief) dan sukarela (kerelawanan). Hal senada berkaitan dengan itu

15
disebutkan Dani Vardiansyah (2008), bahwa keyakinan merupakan suatu sikap yang
ditunjukkan oleh manusia saat merasa cukup mengetahui dan menyimpulkan bahwa
dirinya telah mencapai kebenaran. Pendapat ini dipertegas Schwitzgebel (2006) bahwa
kepercayaan merupakan suatu keadaan psikologis di saat seseorang menganggap
suatu premis benar. Hal kenyakinan, keikhlasan, dan kepercayaan yang diakui masing-
masing stakeholders LKS sebagai tanda bukti patuh pada Firman Tuhan menurut kitab
suci agama masing-masing; sedangkan kerelawanan, kesetiakawanan, kemitraan,
akuntabilitas, profesionalisme, partisipasi, keterbukaan, keterpaduan, keadilan, dan
keberlajutan diakumulasi oleh pemerintah, seperti tersirat pada Pasal 2 UU No 11
Tahun 2009.
Pedoman sistem nilai yang dinyakini di atas dapat menjadi benteng moral yang
tangguh bagi manusia untuk melakukan pekerjaan amal dan pekerjaan kemanusiaan.
Apabila kedua pekerjaan tersebut tidak sejalan dengan kenyakinannya, LKS tersebut
akan ditinggalkan; dan sebaliknya, kedua pekerjaan tersebut dinyakini sejalan dengan
kenyakinannya maka sistem nilai tersebut benar-benar secara sungguh-sungguh
diimplementasikan. Namun, tatkala nilai moral tersebut hanyalah sekedar sampai pada
tahapan wacana, terlebih jika hanya menjadi suatu sistem nilai yang mengikat segenap
pihak di dalam suatu LKS atau organisasi, maka sistem nilai moral sebaik apapun tidak
akan berdampak pada perilaku manusia secara individual. Pengimplementasian sistem
nilai pada kehidupan lembaga sehari-hari memerlukan beberapa prasyarat, yaitu:
adanya motivasi yang kuat, nilai moral dibangun secara sistematik dengan dilandasi
dasar keyakinan yang kuat, sistem nilai dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan
ekonomi, serta perlu didukung oleh sistem hukum dan pengawasan yang efektif
(Chapra dan Ahmed, 2002).
Sistem nilai moralitas yang disebutkan sebelumnya itu berkaitan dengan
kesadaran terhadap kewajiban berbagi, dan beramal dinyakini sebagai pilihan
perbuatan terbaik. Hal ini “terpola bahwa harta kita sebagian menjadi hak orang lain”,
serta prinsip hidup membantu orang lain sebelum kita kaya tersirat dalam Firman
Allah SWT. dan Hadis Nabi SAW. Dan Bagi keluarga Nasrani hal penghimpunan
persembahan sukarela bagi kepentingan orang miskin, tercatat dalam Kitab Injil bahwa
penghimpunan persembahan sukarela yang ikhlas-bebas-pantas tersebut dapat
disalurkan melalui kolekte mingguan dan persembahan sukarela kepada: Gereja
Paroki, lembaga-lembaga sosial, posko bencana, seminari, dan lain-lainnya. Bagi umat
Hindu Kitab Sarasa Muccaya Dana-punya merupakan dasar berperilaku memberikan
donasi untuk kepentingan sesame (Kanjeng, 1977).
Melalui aspek internal dapat dibangun sistem bermakna, bahwa diperlukan
batasan tegas berkaitan dengan cakupan tanggungjawab, seperti mekanisme berkenaan
dengan target kerja yang dapat mempengaruhi imbalan, penghargaan, dan hukuman
pada semua pihak yang terlibat dalam sistem tersebut (Syalan, 2013). Sistem akan

16
menjadi efektif tatkala para pelaku yang terlibat memiliki dasar keyakinan sama,
bahwa segala apa yang menjadi tanggungjawabnya harus dipertanggungjawabkan tidak
hanya pada level dunia, melainkan juga sampai dengan perihal yang bersifat
ukhrowiah pada kehidupan akhirat.
Dalam hal ini, faktor eksternal sistem harus disadari sejak awal meskipun
aspek internal sudah kondusif, tetapi tetap perlu memperhatikan lingkungan sosial,
politik, dan ekonomi karena akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak
langsung kondisi internal sistem yang dibangun tersebut. Berkaitan dengan hal ini,
fenomena sangat lemahnya norma perilaku dan penegakan norma di dalam LKS
disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan
pemahaman ilmu agama, dan keterbatasan relasi. Akibatnya, terjadi patologis birokrasi
secara sistemik sehingga mempengaruhi penurunan layanan kesejahteraan dan
degradasi moral. Kondisi lingkungan seperti itu perlu dibuatkan mekanisme regulasi
dan supervisi yang lebih efektif (Chapra dan Ahmed, 2002).
Stakeholder pemeran kunci korporasi LKS
Faktor penting yang diperlukan untuk mewujudkan mekanisme korporasi
tatakelola yang efektif di lembaga kesejahteraan sosial memiliki unit-unit yang
berkaitan dengan: pengurus/Board of Director (BOD) dengan manajemen, kontrol
internal, manajemen risiko yang efektif, dan tingkat transparansi yang tinggi, serta
standar akunting dan audit. Menurut Chapra dan Ahmed (2002), bahwa BOD memiliki
peran penting pada korporasi tatakelola yang penekanannya lebih pada integritas moral
daripada kemampuan teknis, tetapi harus paham dengan risiko dan kompleksitas pasar
filantropi serta upaya untuk meningkatkan kapasitas berkaitan dengan profesi tersebut
maupun dengan landasan kerja amal dan landasan kerja kemanusiaan.
Berbicara mengenai tugas BOD, antara lain 1) melakukan pertemuan secara
regular, 2) melakukan kontrol efektif tentang kondisi layanan, sarana prasarana
layanan, keuangan LKS, 3) diskusi secara intensif dengan senior manajemen dan
internal audit, 4) membuat aturan main, memonitor perkembangan pencapaian tujuan
lembaga keuangan.
Selain itu, BOD juga melakukan, pengawasan sesuai dengan tupoksi yang
dikeluarkan oleh otoritas pengawasan dan melakukan modifikasi jika dianggap perlu,
mampu menjelaskan tujuan strategis secara spesifik, memandu pasar filantropi, kode
etik untuk senior manajemen dan standar kerja staf. Eksistensi BOD ditentukan oleh
kemampuannya membangun sistem kontrol internal yang kuat, manajemen risiko yang
efektif, membuat semua prosedur dan regulasi serta peraturan yang penting khususnya
berkaitan dengan rekruitmen senior manajemen yang bebas dari nepotisme dan
favoritisme berdasarkan kemampuan real yang terukur (merit sistem).

17
Adapun tugas senior manajemen bertanggungjawab atas fungsi keseharian
lembaga agar dapat beroperasi secara sehat dan efektif dengan membuat sistem internal
audit, prosedur kontrol, dan manajemen risiko. Sistem internal auditor dibuat oleh
senior manajer berdasarkan atas keterampilan dan kompetensi teknis yang cukup, serta
bersikap independen sehingga dibebastugaskan dari pekerjaan yang bersifat
operasional. Internal auditor secara regular melaporkan kinerja lembaga kepada BOD
maupun manajemen, dan BOD harus berperan agar internal audit tidak di bawah
tekanan manajemen. Apabila hasil audit internal menunjukkan hal-hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh manajemen, BOD harus mendorong manajemen untuk
melakukannya.
Berdasarkan hal tersebut di atas Syaflan (2013) menyebutkan tiga kriteria
minimum bagi manajemen yang baik dalam bahasa agama, yaitu siddik, amanah,
fathonah, dan terhindar dari tiga sifat munafik. Pada prinsipnya ketika manajemen
mulai melakukan penipuan atau penyimpangan, maka mereka mulai merajut suatu
keruwetan di sekitar dirinya sendiri, oleh karena itu upaya peningkatan kejujuran perlu
dilakukan, seperti sikap disiplin dan dapat dipercaya, para petugas dan staf hemat serta
cermat, internal kontrol yang efektif karena dapat menekan benih kecurangan dan
mendorong tumbuhnya whistle blowers (pelaporan malpraktik/kebohongan).
Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem
yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan dan perintah serta peraturan yang
berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang
telah ditetapkan tanpa pamrih.
Internal kontrol yang efektif, selain dapat menekan benih kecurangan juga
dapat memahami permasalahan dan kekurangan yang terjadi di dalam lembaga,
kemudian memacu pihak manajemen menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah.
Tatkala sistem ini berlangsung akan mendorong pihak manajemen menyusun strategi
perencanaan dan kesiapan diri serta kebersamaan yang lebih berorientasi pada
pertimbangan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek untuk kesuksesan dan
antisipasi permasalahan di waktu yang akan datang. Dalam kaitan ini, Olsen dan Eadie
(1982) mengatakan bahwa dukungan dan komitmen orang-orang penting pembuat
keputusan merupakan hal yang vital. Salah satu indikasinya rencana strategis
berorientasi pada pertimbangan jangka panjang adalah manajemen memberikan
prioritas tinggi untuk kegiatan peningkatan kapasitas, baik untuk pendidikan dan
pelatihan maupun bagi investasi untuk mengadopsi teknologi dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga terbangun citra yang baik bagi
lembaga (Chapra & Ahmed, 2002).
Mendorong terbangun serta tumbuhnya whistle blowers berkaitan dengan
kesadaran bersama untuk saling mengingatkan agar pihak internal tidak berupaya
melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan yang berlaku, karena hal itu akan

18
menimbulkan keberanian pihak internal lainnya untuk menyuarakan indikasi atau
penyimpangan tersebut. Dengan demikian, diperlukan kebijakan khusus untuk
membangun suasana kondusif bagi tumbuhnya whistle blower tersebut karena dapat
menimbulkan situasi tidak nyaman, kekerasan, dan bahkan sampai dapat
menghilangkan pekerjaan seseorang.
Pada lembaga LKS pemegang saham adalah pasar filantropi yang
mendonasikan sebagian hartanya, para donatur tidak pernah berpikir tentang risiko
apabila tidak mengharapkan keuntungan materi atau menarik modal sehingga tidak
memiliki risiko apapun, dan sesama donatur belum tentu saling mengenal satu sama
lain. Atas dasar itu, LKS sebagai lembaga yang dipercaya oleh para donatur melalui
agen yang dipercaya untuk mengelola donasi tersebut, perlu membangun transparansi
yang tinggi kepada pasar filantropi, dan jika diketahui terjadi whistle blower di LKS
akan dihentikan donasinya. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diantisipasi secara
dini sangatlah berisiko karena dapat mempengaruhi secara sistemik ketika terjadi
penghentian masal, sebab dana LKS sebagian besar berasal dari pasar filantropi.
Namun, selama ini hak pasar filantropi tersebut relatif diabaikan, artinya para donatur
belum pasti mendapatkan laporan atau informasi tentang operasional donasinya.
Dengan demikian, peningkatan kualitas korporasi tatakelola pada lembaga
kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keterbukaan pada
model keterwakilan para donatur tersebut di BOD. Perihal mekanisme penyerahan
donasi serta mekanisme penyaluran donasi semestinya transparan dan akan lebih baik
jika setiap kelompok pasar filantropi memahaminya dan mendapatkan informasi atau
laporan perjalanan donasi tersebut, walaupun sebagian donatur tidak ingin mengetahui
perjalanan donasinya sebab percaya bahwa LKS akan menyalurkan donasinya secara
benar (BK3S DIY, 2005).
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemeran kunci pada LKS terdiri dari
kelompok Bord yang terdiri dari Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan,
Kelompok Eksekutif LKS terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan urusan bidang
sesuai dengan kebutuhan LKS masing-masing, Pihak eksternal terdiridari pasar
filantropi, Pemerintah, masyarakat dan keluarga klien.
Penghambat Responsibilitas
Ditemuka enam kelemahan penerapan prinsip good corporate governance
pada lembaga kesejahteraan sosial di DIY, yaitu :
1. Lemahnya pemerintah dan supra LKS dalam melakukan control terhadap LKS.
2. Tingginya tolerensi masyarakat di sekitar LKS, dalam hal ini masyarakat kurang
peduli terhadap keberdaan LKS.

19
3. Lemahnya peranan the board of directors dalam mengendalikan pengelolaan
organisasi. Board of directors kurang aktif dalam menganalisis startegi
management organisasi.
4. Sebagian merasa bebas mengelola donatur, karena donatur tidak pernah melakukan
audit, mereka percaya bahwa donasinya disalurkan secara baik dan benar. Sehingga
pengambilan keputusan–keputusan penting yang bersangkutan dengan
kelangsungan hidup organisasi.
5. Tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan
organisasi dan keuangan oleh board of directors kepada pendiri dan pasar
filantropi.
6. Problem auditor, banyak LKS yang belum melakukan melakukat audit atas donatur,
baik donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Ketakutan pengurus akan kelemhan
atau penyimpangan atas pengunaan donasi.
Pendorong Responsibilitas
Corporate governance menurut John dan Alan (2011) adalah subjek yang
memiliki banyak aspek. Tema utama dari corporate governance adalah masalah
akuntabilitas dan tanggung jawab mandat. Aspek lain dari corporate governance
seperti sudut pandang pemangku kepentingan atau stakeholders yang menuntut
perhatian, transparansi, pertanggungjawaban atau responsibilitas serta keadilan lebih
terhadap pihak-pihak selain pasar pilantropi misalnya terhadap karyawan, masyarakat,
relawan dan lingkungan. Perhatian terhadap praktik tata kelola organisasi nonprofit
telah meningkat, sebagi bukti adanya kekwatiran terhadap:
1. Kebutuhan internal, adanya kesadaran BOD dan Ketua LKS atas upaya pemenuhan
tuntutan eksternal, kesadaran meningkatkan kualitas SDM, berupaya memenuhi
standar pelayanan dan standar fasilitas. Sebagai contoh ada kesadaran BOD
menyekolahkan atau staf untuk memenuhi atauran atas tuntutan eksternal dan
berupaya memenuhi hak-hak klien.
2. Tekanan eksternal
Idealnya LKS yang sehat BOD dan manager tidak ada yang menyembuyikan
informasi dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
dengan tetap memperhatikan etik, atas kewenangan masing-masing. Kenyataan
beberapa LKS belum berani memberikan informasi secara transparan kepada pihak-
pihak yang membutuhkan sebagi bukti ketika LKS diberi burang banyak yang diisi
tidak sesuai dengan fakta dilapangan., ketika ada kebijakan baru untuk menata LKS
masih ada beberapa LKS yang menolak atau kontra, contoh mensosialisasikan
standar nasional anak (SNPA) butuh waktu dua tahun.

20
3. Negara butuh untuk mengatur LKS
Kebijakan Negara yang dibebankan kepada LKS ditanggapi secara pro kontra,
bentuk pro pengelola LKS bersikap aktif mendiskusikan dan mengutarakan
kesulitan selanjutnya mencari jalan keluar bersama. LKS yang kontra tidak
merespon dan pura-pura tidak tahu, bahkan di undang ke Dinas Sosial atau BK3S
tidak hadir tanpa informasi. Disisi lain Dinas Sosial dan BK3S mengundang dalam
rangka memiliki tanggungawab sebagi kebutuhan untuk mengatur dan
mensosialisasikan aturan yang seharusnya dikerjakan para pengelola dalam sifat
yang wajib, contoh LKS waib membuat laporan pertanggugjawaban kepada
pemerintah setiap 4 bulan sekali, enam bulan dan laporan tahunan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Organisasi nirlaba sebagai wujud dari organisasi masyarakat yang berangkat
dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat
menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepentingan pengguna laporan adalah untuk menilai jasa organisasi dan kemampuan
going concern dan menilai cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek
kinerja manajer. Selain itu dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan transparan
memberikan kemudahan manajer untuk membuat suatu pertanggungjawaban kepada
pengguna laporan.
Bentuk-bentuk pelanggaran prinsip pertanggungjawaban (Responsibilitas)
yang teradi pada LKS seperti sulitnya public mengakses informasi donasi dan
pelayanan klien belum memenuhi hak-hak klien sesuai Deklarasi Hak Asasi Manusia
(HAM) atau Universal Independent of Human Righ dicetuskan pada tanggal 10
Desember 1948 dan HAM sesuai dengan UUD 1945.
Pelanggaran dan kejahatan di LKS merupakan pelanggaran dan kejahatan yang
khas yang dilakukan oleh pelaku BOD ataupun manager, sehingga merugian LKS itu
sendiri. Karena dapat menurunkan tingat kepercayaan stakeholder. Pemerintah dan
assosiasi LKS seharusnya memberikan sanksi yang tegas pelaku moral hazard agar
LKS yang menjadi jera Marshall et al (1985), kejahatan korporasi adalah setiap
tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, apakah
di bawah hukum administratif, hukum perdata atau hukum pidana.
Jadi keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat
investor para donatur dan stakeholder lain yang semuanya punya hak atas perlindungan
tersebut. Dari segi substansial, keterbukaan memampukan publik untuk mendapatkan
akses informasi penting yang berkitan dengan perusahaan. Ditinjau dari segi yuridis,
keterbukaan merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses

21
penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.
Pengenaan sanksi yang termuat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 serta
penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan
atau transparansi ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara
hukum dari praktik–praktik manipulasi dalam organisasi publik. Karena keterbukaan
sebagai pertanggungjawaban hukum emiten, perusahaan publik dan perusahaan
terbuka dalam menjalankan keterbukaan informasi kepada investor atau publik. Dalam
kode etik profesi Pekerjaan Sosial dijelaskan bahwa Pekerja Sosial Profesional harus
senantiasa bertindak dengan integritas profesional, yaitu: a. Mewaspadai dan menolak
pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan yang membatasi kebebasan profesionalnya. b.
Tidak menggunakan hubungan profesional demi kepentingan pribadi.
DAFTAR PUSTAKA
Antonius, A dan Subarto, Z., (2004). Komisaris Independence Pengerak Praktek GCG
Di Perusahaan. Penerbit Kota Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
Antonella, S., (2001), Debt as a Device for Corporate Control-the Case of Countries in
Transition. Journal on International Banking Law, Vol. 16 (2). Hlm 48.
Berle, A.A., and Means. G.C., (1932), The Modern Corporation and Private Property.
Macmillan Company, New York.
Cadbury, R., (1992), Report of Committee on The Financial Aspects of Corporate
Governance. Great Britain:Gee.
Chapra, M.U., & Ahmed, H., (2002). Corporate Governance in Islamic Financial
Institutions. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development
Bank, Jeddah.
Charron, D.C., (2007), Stockholder and Stakeholder: The Battle from Control of The
Corporation. Cato Journal; 27,1.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, (2011), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Nomor.45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta:IAI.
Fadilah, A., (2012), Konflik Stakeholders : Studi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pers Mahasiswa Yogyakarta.
Farahmand, Nasser Fegh-hi. (2011). Organizational Technology Management by
Humanware as Important Technology Factor. Research on Humanities and
Social Sciences www.iiste.org ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484
(Online) Vol.1, No.3, 2011.

22
Financial Accounting Standards Board, (1980), Statements of Financial Accounting
Concepts No. 4 Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness
Organization. USA:.FASB.
Hayden, G., and Court, J., (2004), Governance and Development: World Governance
Survey Discussion Paper 1: United NationUniversity.
John, L and Alan, D., (2011), Company Law. Edisi ke 7, Oxford, University Press.
John, C., (1977), Reinenting Your Board (san Francisco: Jossey-Baa, 1977), p.18.
Kadjeng, I.N., dkk, (1977), Sarasamuccaya, C.V. Junasco. Jakarta.
Kooskora, M., ( 2008), Corporate Governance from the stakeholder perspective, in the
context of Estonian business organizations. Baltic Journal of Management.
Vol. 3 No. 2, pp.193-217.
La Porta, R., Lopez-de Silanes, F.,& Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Arund
the World . Journal of Finance, 54, 471-517.
Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager., (1985), Corporate Ethics And Crime The
Role Of Middle Management, Sage Publications. USA.
Mason, M., & O’ Mahoney, J., (2008), Post-traditional Corporate Governance. The
Journal of Corporate Citizenship; Autumn 2008;31.
Meth. Kusumahadi, (2011), Posisi dan Langkah Strategis BK3S-DIY Dimasa
Mendatang, Satunama, Yogyakarta.
Zulkhibri, M., (2014), Regulation governing non-profit organizations in developing
countries: A comparative analysis, International Journal of Lawa and
Management, Vol. 56 Issue: 4, pp 251-273.
Olsen, J. B., and Eadie, D.C., (1982), The Game Plan : Governance with Foresight.
Washington : Council of Stare Planning Agencies.
Pierre, J., and Peters, B.G., (2002), Governance, Politics and the State. New York: St.
Martin’sPress-Reno.
Syaflan, M., (2013), Tipologi Governance Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Daerah
Istimewa Yogyakarta, Desertasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia.
Sektiono, D., and Nugraheni, R., (2016), Implementasi Good Governance Lembaga
Swadaya Masyarakat. Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang
Semarang. Universitas Diponegoro, Semarang Indonesia.

23
Schwitzgebel, E., (2006), "Belief", di Zalta, Edward, The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, Stanford, CA: The Metaphysics Research Lab, diakses tanggal 2-
11-2016.
Sheffied J. and White, S., (2004), Control self-assessment as a route toorganizational
excellence: AScottish Housing Association Case Study Managerial Auditting
Journal: 19,4;pg.484.
Sugiyanto, (2018), Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial. Studi kasus
di LKS Mardi Wuto dan Hamba DIY. Desertasi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia.
Sukariyadi, U., (2014), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial DIY, Dinas Sosial Daerah Iistimew Yogyakarta.
Taylor, F.W., (1967), The Principles of Scientific Management, The Narton. Library.
New York.
Thomas, C., (1910), The Modern Corporation, Then Ronald Press. New York.
Vardiansyah, D., (2008), Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta.
Voss, G.L., (1976), Seashore life of florida and the Carribbean. Banyan Books, Inc.
Miami, Florida.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akriditasi
Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar
Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002
tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN.