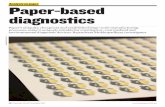Paper Witjak
-
Upload
andrifadillahm -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of Paper Witjak
J. Biol. Indon. Vol 8, No.1 (2012) ISSN 0854-4425 ISSN 0854-4425
JURNAL JURNAL BIOLOGI BIOLOGI INDONESIA INDONESIAAkreditasi: No 816/D/08/2009 Vol. 8, No. 1 Juni 2012Anthropogenic Influences on The Sosioecology of Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Lombok Island, Indonesia Islamul Hadi, Bambang Suryobroto, & Kunio Watanabe The Dynamics of Species Composition Stand Structure and Above Ground Biomass of Undisturbed Forest in East Kalimantan Haruni Krisnawati, Djoko Wahjono & Rinaldi Imanuddin Apis koschevnikovi: Distribution in South Kalimantan and Cytochrome b Mitochondrial DNA Variations Jazirotul Fitriya, Rika Raffiudin, Tri Atmowidi, & Randall Hepburn Reproduksi Ikan Endemik Butini (Glossogobius matanensis Weber 1913) Berdasarkan Kedalaman dan Waktu di Danau Towuti, Sulawesi Selatan Jefry Jack Mamangkey & Syahroma Husni Nasution Perubahan Persentase Unsur Hara Serasah Akibat Proses Dekomposisi Pada Empat Spesies Tanaman Gugur Daun di Kebun Raya Purwodadi Agung Sri Darmayanti & Ridesti Rindyastuti Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Keragaman dan Pola Distribusi Kumbang Sungut Panjang (Coleoptera: Cerambycidae)di Gunung Salak Jawa Barat Woro Anggraitoningsih Noerdjito Pelestarian Lingkungan Berbasis Kepercayaan Lokal dan Upacara Tradisi: Studi Kasus Masyarakat di Sekitar Gunung Salak Mohammad Fathi Royyani & Eko Baroto Walujo Efikasi Cendawan Entomopatogenik Untuk Mengendalikan Ulat Bulu Yusmani Prayogo, Marwoto & Suharsono 1
9
23
31
45
57
71
85
BOGOR, INDONESIA
J. Biol. Indon. Vol 8, No. 1 (2012)Jurnal Biologi Indonesia diterbitkan oleh Perhimpunan Biologi Indonesia. Jurnal ini memuat hasil penelitian ataupun kajian yang berkaitan dengan masalah biologi yang diterbitkan secara berkala dua kali setahun (Juni dan Desember). Editor Pengelola Dr. Ibnu Maryanto Dr. I Made Sudiana Deby Arifiani, S.P., M.Sc
Dr. Izu Andry FijridiyantoDewan Editor Ilmiah Dr. Abinawanto, F MIPA UI Dr. Achmad Farajalah, FMIPA IPB Dr. Ambariyanto, F. Perikanan dan Kelautan UNDIP Dr. Aswin Usup F. Pertanian Universitas Palangkaraya Dr. Didik Widiyatmoko, PK Tumbuhan, Kebun Raya Cibodas-LIPI Dr. Dwi Nugroho Wibowo, F. Biologi UNSOED Dr. Parikesit, F. MIPA UNPAD Prof. Dr. Mohd.Tajuddin Abdullah, Universiti Malaysia Sarawak Malaysia Assoc. Prof. Monica Suleiman, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia Dr. Srihadi Agungpriyono, PAVet(K), F. Kedokteran Hewan IPB Y. Surjadi MSc, Pusat Penelitian ICABIOGRAD Drs. Suharjono, Pusat Penelitian Biologi-LIPI Dr. Tri Widianto, Pusat Penelitian Limnologi-LIPI Dr. Witjaksono Pusat Penelitian Biologi-LIPI Alamat Redaksi
Sekretariatd/a Pusat Penelitian Biologi - LIPI Jl. Ir. H. Juanda No. 18, Bogor 16002 , Telp. (021) 8765056 Fax. (021) 8765068 Email : [email protected]; [email protected] Website : http://biologi.or.id Jurnal ini telah diakreditasi ulang dengan nilai A berdasarkan SK Kepala LIPI 816/ D/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
J. Biol. Indon. Vol 8, No.1 (2012)DAFTAR ISIAnthropogenic Influences on The Sosioecology of Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Lombok Island, Indonesia Islamul Hadi, Bambang Suryobroto, & Kunio Watanabe The Dynamics of Species Composition Stand Structure and Above Ground Biomass of Undisturbed Forest in East Kalimantan Haruni Krisnawati, Djoko Wahjono & Rinaldi Imanuddin Apis koschevnikovi: Distribution in South Kalimantan and Cytochrome b Mitochondrial DNA Variations Jazirotul Fitriya, Rika Raffiudin, Tri Atmowidi, & Randall Hepburn Reproduksi Ikan Endemik Butini (Glossogobius matanensis Weber 1913) Berdasarkan Kedalaman dan Waktu di Danau Towuti, Sulawesi Selatan Jefry Jack Mamangkey & Syahroma Husni Nasution Perubahan Persentase Unsur Hara Serasah Akibat Proses Dekomposisi Pada Empat Spesies Tanaman Gugur Daun di Kebun Raya Purwodadi Agung Sri Darmayanti & Ridesti Rindyastuti Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Keragaman dan Pola Distribusi Kumbang Sungut Panjang (Coleoptera: Cerambycidae)di Gunung Salak Jawa Barat Woro Anggraitoningsih Noerdjito Pelestarian Lingkungan Berbasis Kepercayaan Lokal dan Upacara Tradisi: Studi Kasus Masyarakat di Sekitar Gunung Salak Mohammad Fathi Royyani & Eko Baroto Walujo Efikasi Cendawan Entomopatogenik Untuk Mengendalikan Ulat Bulu Yusmani Prayogo, Marwoto & Suharsono Sirkulasi virus Avian influenza H5N1 Tahun 2010 : Virus genetic drift mirip A/Ck/West Java/Pwt-Wij/2006 ditemukan di beberapa kabupaten di Sumatra dan Jawa NLP Indi Dharmayanti, Atik Ratnawati, Dyah Ayu Hewajuli, & Risa Indriani Peroksidasi Lipida oleh Parasetamol dan Ekstrak Air Panas Teh Hijau (Camellia sisnensis ) pada Sel Khamir Candida tropicalis yang Di simpan pada Suhu Rendah Heddy Julistiono Keragaman Genetik Rusa Sambar (Rusa unicolor), Pemanfaatan dan Implikasinya Untuk Konservasi Wirdateti 1
9
23
31
45
57
71
85
103
121
131
J. Biol. Indon. Vol 8, No. 1 (2012)Kualitas Daging dan Bagian Tubuh Lain Trenggiling (Manis javanica Desmarest, 1822) Wartika Rosa Farida Small Mammals Diversity in Kawah Ratu Resort, Mount Salak, West Jawa, Indonesia Maharadatunkamsi Iradiasi Sinar g pada Biak Tunas Kentang Hitam (Solanostemon rotundifolius) Efektif untuk Menghasilkan Mutan Witjaksono &Aryani Leksonowati Persilangan Pisang Liar Diploid Musa acuminata Colla var malaccensis (RIDL.) Nasution Sebagai Sumber Polen dengan Pisang Madu Tetraploid Yuyu S. Poerba, Fajarudin Ahmad & Witjaksono TULISAN PENDEK Satu Dekade Kondisi Hutan Mangrove di Teluk Ambon, Maluku Suyadi Morfologi Organ Testis pada Ular Pelangi Xenopeltis unicolor Boie, 1827 (Serpentes : Xenopeltidae) Mumpuni 141
155
167
181
197
203
Jurnal Biologi Indonesia 8(1):167-179 (2012)
Iradiasi Sinar pada Biak Tunas Kentang Hitam (Solanostemon rotundifolius) Efektif untuk Menghasilkan MutanWitjaksono & Aryani LeksonowatiPusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor-Jakarta Km 46, Cibinong, Bogor. Telp/Fax : (021) 8765066 / (021) 8765067 Email : [email protected] ABSTRACT Irradiation of ray at shoot culture of Kentang hitam (Solanostemon rotundifolius) is effective for mutant production. Kentang hitam is sterile and vegetatively propagated and therefore its genetic diversity is narrow. Mutation is an alternative way to increase genetic heterogeneity. Irradiation of shoot cultures with different doses followed by culturing of the inoculum (leaf, petiole and internodes) from that irradiated culture on a regeneration medium MS containing 5 mg/l BA and 0.1 mg/l NAA has resulted in curvilinear respon of growth, morphogenesis and plant regeneration. The growth variables increase from 0 to 6 Gy and then decrease to 25 and plateu or increase a little at 35 Gy and growth death wes observed at 50 Gy. Leaf and petiole inocula were more responsive than the internode. Respon of growth of shoot regeneration of 50% were obtained at doses of 10-12.5 Gy. However higher level of doses, such as 25 Gy had also been effective for inducing mutant. Morphological and growth different were observed from growth in tissue culture to the field. Mutants were recovered, for example, the one with early flowering. Keywords : Solanostemon rotundifolius, Irradiation, gammarays, cultur in vitro, mutan
PENDAHULUANKentang hitam (Solanostemon rotundifolius (Poir) JK Morton) merupakan salah satu sumber karbohidrat alternatif yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Umbinya mengandung 20% karbohidrat (terutama pati) dan sekitar 2% protein. Kentang hitam temasuk dalam suku Lamiaceae dan tidak seperti kentang (Solanum tuberosum) yang termasuk dalam suku Solanaceae. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, resisten terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur namun
sangat peka terhadap nematoda (Jansen 1996). Kentang hitam, belum populer di masyarakat Indonesia, hanya dikenal oleh penduduk di pulau Jawa, Bali dan Madura (Heyne 1987). Di Indonesia maupun di Afrika, kentang hitam dipakai sebagai pengganti kentang dikonsumsi sebagai sayur, makanan samping dan bahkan sebagai bahan pencampur dalam industri farmasi (Jansen 1996). Tanaman ini diperbanyak secara vegetatif dengan umbinya maupun stek batang. Tanaman ini biasa berbunga, tetapi tidak menghasilkan biji karena polennya steril (Vimala & Nambisan 167
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
Iradiasi Sinar Jpada Biak Tunas Kentang Hitam (Solanostemon rotundifolius) Efektif untuk Menghasilkan MutanWitjaksono & Aryani LeksonowatiPusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor-Jakarta Km 46, Cibinong, Bogor. Telp/Fax : (021) 8765066 / (021) 8765067 Email : [email protected] ABSTRACT Irradiation of Jray at shoot culture of Kentang hitam (Solanostemon rotundifolius) is effective for mutant production. Kentang hitam is sterile and vegetatively propagated and therefore its genetic diversity is narrow. Mutation is an alternative way to increase genetic heterogeneity. Irradiation of shoot cultures with different doses followed by culturing of the inoculum (leaf, petiole and internodes) from that irradiated culture on a regeneration medium MS containing 5 mg/l BA and 0.1 mg/l NAA has resulted in curvilinear respon of growth, morphogenesis and plant regeneration. The growth variables increase from 0 to 6 Gy and then decrease to 25 and plateu or increase a little at 35 Gy and growth death wes observed at 50 Gy. Leaf and petiole inocula were more responsive than the internode. Respon of growth of shoot regeneration of 50% were obtained at doses of 10-12.5 Gy. However higher level of doses, such as 25 Gy had also been effective for inducing mutant. Morphological and growth different were observed from growth in tissue culture to the field. Mutants were recovered, for example, the one with early flowering. Keywords : Solanostemon rotundifolius, Irradiation, gammarays, cultur in vitro, mutan
PENDAHULUANKentang hitam (Solanostemon rotundifolius (Poir) JK Morton) merupakan salah satu sumber karbohidrat alternatif yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Umbinya mengandung 20% karbohidrat (terutama pati) dan sekitar 2% protein. Kentang hitam temasuk dalam suku Lamiaceae dan tidak seperti kentang (Solanum tuberosum) yang termasuk dalam suku Solanaceae. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, resisten terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur namun
sangat peka terhadap nematoda (Jansen 1996). Kentang hitam, belum populer di masyarakat Indonesia, hanya dikenal oleh penduduk di pulau Jawa, Bali dan Madura (Heyne 1987). Di Indonesia maupun di Afrika, kentang hitam dipakai sebagai pengganti kentang dikonsumsi sebagai sayur, makanan samping dan bahkan sebagai bahan pencampur dalam industri farmasi (Jansen 1996). Tanaman ini diperbanyak secara vegetatif dengan umbinya maupun stek batang. Tanaman ini biasa berbunga, tetapi tidak menghasilkan biji karena polennya steril (Vimala & Nambisan 167
Witjaksono &Leksonowati
2005). Sterilitas polen tersebut disebabkan karena ketidaknormalan sitogenetik yang meliputi disinapsis (Vasudevan et al 1967 dalam Vimala & Nambisan 2005), meiosis tidak teratur (Ramachandran 1967 dalam Vimala & Nambisan 2005), sehingga dapat diperkirakan keragaman genetik kentang hitam sempit. Peningkatan keragaman genetik tanaman yang secara alamiah sempit dapat dilakukan dengan manipulasi sel somatik seperti misalnya induksi variasi somaklonal, mutasi, hibridisasi somatik dan transformasi genetik. Pemuliaan mutasi telah banyak menghasilkan varietas baru (Anonymous 1970). Keragaman genetik yang terinduksi karena mutasi selanjutnya dapat dilestarikan dalam bentuk varietas melalui perbanyakan vegetatif. Generasi ke-2 ginseng Jawa hasil mutasi mempunyai biomasa akar delapan kali biomasa tanaman kontrol (Poerba 2004). Induksi mutasi pada mawar menghasilkan mutan mawar dengan warna putih dan merah di pinggirnya (Soedjono 2003). Sedangkan iradiasi sinar gamma pada Curcuma alismatifolia menimbulkan keragaman waktu munculnya tunas yang menjadi lebih lama, perubahan klorofil daun dan morfologi bunga (Abdullah et al. 2009). Iradiasi ruas batang dengan satu buku dilaporkan menghasilkan keragaman produksi umbi kentang hitam (Abraham & Radakhrisnan 2009). Induksi mutasi melalui kultur jaringan dapat diarahkan untuk mendapatkan genotipe yang lebih baik dari induknya seperti ukuran umbi lebih besar, kualitas umbi/tepung yang lebih baik, kandungan bahan aktif yang lebih 168
tinggi, tahan hama/penyakit atau karakter tanaman. Induksi mutasi in vitro pada sel-sel yang mampu beregenerasi akan menghasilkan mutan utuh dan tidak memerlukan pemisahan khimera. Karena jumlah sel yang menyusun suatu organ daun banyak, maka mutasi pada daun juga akan menimbulkan banyak sel mutan yang selanjutnya beregenerasi menjadi tanaman mutan dalam jumlah banyak. Regenerasi kentang hitam secara kultur jaringan telah berhasil dilakukan baik melalui perbanyakan tunas samping maupun regenerasi melalui tunas adventif baik langsung (Leksonowati & Witjaksono 2012) maupun tidak langsung yaitu melalui kalus (Hoesen 1991; Prematilake 2005). Tanaman kentang hitam sangat responsif terhadap manipulasi in vitro; tanaman yang diregenerasi dari kalus menunjukkan variasi somaklonal (Prematilake 2005). Oleh karena itu protokol induksi mutasi dan regenerasi tanaman kentang hitam in vitro diperlukan karena diperkirakan dapat dipakai untuk meningkatkan keragaman genetik kentang hitam. BAHAN DAN CARA KERJA Bahan tanaman yang digunakan dalam percobaan iradiasi ini berupa biak kentang hitam aksesi Nganjuk 1 umur 67 minggu yang ditumbuhkan pada botol biak berukuran 100 ml dan diisi 25 ml medium tumbuh formulasi MS (Murashige & Skoog 1962) yang dimodifikasi dan terdiri dari (mg/l): KNO 3 1900, NH 4 NO 3 1650, CaCl 2 .2H2O 440, MgSO4.7H2O 370, KH 2 PO 4 170, hara mikro, vitamin
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
(Glycine 4, Pyrodixine 1, Thiamin 0.2, Nicotinic acid 0.5), sukrosa 30.000 dan zat pengatur tumbuh BA 0,5 dan NAA 0,1 (Leksonowati & Witjaksono 2012). Medium dipadatkan dengan 3 g/l Gelrite. Medium tumbuh diatur dengan 0,1 N HCl atau KOH sehingga pH menjadi 5.7-5.8 sebelum ditambah Gelrite. Medium kemudian diautoklaf pada suhu 121oC dan tekanan 15 Psi selama 20 menit. Biak dipelihara di dalam ruang pemeliharaan biak dengan suhu 25oC pada rak kultur dengan intensitas cahaya sekitar 261-352 lux selama 16 jam per hari. Percobaan iradiasi dengan sinar gamma dengan dosis 0, 6, 12.5, 25, 35 dan 50 Gray dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional, Jl.Lebak bulus, Jakarta. Iradiasi dipaparkan pada biak tunas dalam botol aksesi Nganjuk 1. Paling lama sehari kemudian biak yang telah diiradiasi dipakai sebagai sumber bahan tanaman (inokulum). Inokulum berupa potongan daun, tangkai daun dan ruas batang diambil dari biak yang telah diradiasi disubkultur di medium regenerasi yang mempunyai formulasi MS seperti pada medium biak tunas tetapi dengan zat pengatur tumbuh 5 mg/l BA dan 0.1 mg/ l NAA yang diwadahi dalam petridish 100 x 20 mm. Inokulum daun yang dipakai berukuran sekitar 0,5 cm2, dan diambil dari posisi kedua sampai dengan empat dari pucuk pada batang (Suherlina et al. 2012). Daun dipotong pada keempat sisinya. Jika berukuran besar, daun dibagi menjadi 2-6 potongan. Potongan daun ditanam dengan posisi tengkurap (adaksial kontak medium). Sedangkan inokulum tangkai dan ruas batang
berukuran panjang 0.5-1 cm. Tiap perlakuan iradiasi terdiri dari 5 ulangan, dan masing-masing ulangan diisi 10-14 inokulum. Biak disimpan dalam ruang pemeliharaan biak seperti pada biak tunas tersebut di atas. Pengamatan pertumbuhan biak yang meliputi persentase inokulum hidup, membentuk kalus, tunas, dan jumlah tunas dilakukan pada minggu ketiga sejak inokulum ditanam pada medium regenerasi. Tahapan ini inokulum belum mengalami subkultur dan karena itu dinamai subkultur ke-0 (S0). Nilai LD50 (lethal dose 50%) ditentukan dari persentase inokulum yang hidup sebanyak 50% dari kontrol tanpa iradiasi. Tunas yang tumbuh pada inokulum yang diuji, diamati pertumbuhannya (kalus atau tunas) pada umur 6 minggu. Pembentukan kalus merupakan respon pertumbuhan karena itu dalam hubungannya dengan dosis iradiasi, ukuran dari pertumbuhan yang mencapai 50% dari kontrol dinamai dosis respon 50% atau disingkat RD50 (Response dose 50%). Penamaan ini mengikuti dosis proliferasi kalus yang menunjukkan pertumbuhan kalus dibandingkan kontrol tanpa radiasi (Witjaksono & Litz 2004). Data disajikan dalam grafik regresi yang dibuat dengan program Sigma Plot ataupun histogram dengan error bar yang dibuat dengan program Excel. Tunas-tunas yang tumbuh dari inokulum awal (daun, potongan) dipisahpisah menjadi beberapa tunas/clump kemudian disubkultur ke medium pembesaran dengan formulasi yang sama dengan medium regenerasi tetapi tanpa zat pengatur tumbuh. Pada 169
Witjaksono &Leksonowati
subkultur yang pertama ini (S1), pengamatan pertumbuhan biak dilakukan setelah berumur 2 bulan terhadap jumlah dan tinggi tunas. Selain itu dilakukan juga pengamatan terhadap perubahan morfologi biak setelah iradiasi. Biak tunas pada medium tanpa zat pengatur tumbuh yang telah berumur 6 minggu dibersihkan dari agar medium dengan menambahkan air ke dalam botol kultur dan dengan hati-hati mengeluarkan tunas sehingga tidak banyak akar yang rusak. Selanjutnya akar planlet tersebut dicuci dengan air mengalir kemudian direndam larutan fungisida Benstar (bahan aktif benlate) dan bakterisida Agrept (bahan aktif agrimicin) sesuai dosis rekomendasi. Planlet ditanam dalam bak plastik berukuran 45 x 35 x 15 cm yang telah diisi dengan medium campuran sekam: tanah: pasir: cocopeat (2:1:5:9). Medium ditanak 6 jam untuk pasteurisasi sebelum dipakai. Bak plastik dengan planlet di dalamnya di tutup plastik bening dan diikat dengan tali karet untuk mempertahankan kelembaban. Planlet disiram 2 g/l larutan pupuk Growmore (15N-15P-15K) seminggu sekali. Sesekali tutup plastik dibuka untuk memeriksa kelembaban medium dan disiram air bila perlu. Bak aklimatisasi di letakkan di greenhouse yang pada atapnya ditutup paranet 65%. Setelah 4-6 minggu daun baru tumbuh pada plantlet dan plastik dibuka dan biak dibiarkan selama 2 minggu untuk beradaptasi dengan kelembaban udara ambient sebelum ditranplant di polibag. Planlet yang telah berakar dari bak aklimatisasi di tanam pada medium transplanting dalam polibag yang terdiri 170
dari tanah : kompos : arang sekam (4:5:1). Bibit transplant dipelihara di dalam greenhouse dengan naungan 65% selama 4-6 minggu. Pengamatan terhadap aklimatisasi dan transplanting yang dilakukan pada percobaan ini dilakukan pada saat yang sama, bukan dari percobaan yang berurutan. Karena itu data dari jumlah tanaman di polibag tidak berasal dari jumlah planlet dari pengamatan aklimatisasi. Jumlah total bibit dari bak aklimatisasi dan polibag menunjukkan jumlah keseluruhan bibit/tanaman dari percobaan irradiasi yang dilakukan. Bibit tranplant setelah berumur 4-6 minggu di tanam di lapang dengan jarak tanam 50 cm. Tanah diolah, digemburkan dan dibentuk guludan dan diberi pupuk kandang sebanyak 25 kg/meter 2 . Tanaman disemprot dengan Decis secara rutin untuk melindungi dari hama ulat dan serangga. Pada musim kemarau, tanaman disiram secara berkala untuk menghindari kekeringan. HASIL Pengaruh dosis iradiasi sinar J terhadap daya hidup berbagai inokulum kentang hitam in vitro. Induksi mutasi menggunakan sinar J berbagai dosis terlihat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan daya hidup inokulum. Pertumbuhan inokulum dapat dikelompokkan pada beberapa kategori: sebagian besar berubah menjadi coklat dan mati pada hari pertama pada perlakuan 35 dan 50 Gy, sebagian besar bertahan tetap hijau sampai minggu pertama kemudian
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
menguning atau mencoklat dan mati pada perlakuan 12,5 dan 25Gy, dan sebagian besar bertahan hijau sampai seminggu lalu tumbuh membesar dan membentuk kalus atau tunas pada perlakuan 0 dan 6 Gy. Pada inokulum daun perubahan daya hidup teramati secara nyata (Gambar 1A-C). Sejumlah kecil inokulum pada dosis iradiasi tinggi tetap tumbuh membentuk kalus atau tunas. Analisis regresi dari daya hidup inokulum daun terhadap dosis irradiasi menunjukkan respon curvilinear dengan persamaan Y = 89.9- 1.8X - 0.1X2 dan koefisien korelasi R2 = 0.95. Secara visual, daya hidup inokulum daun meningkat dari dosis 0 ke dosis 6, lalu menurun secara linear mencapai nilai nol ke dosis 25 Gy (Gambar 2 A). Dosis penyebab respon daya hidup sebanyak 50% dari kontrol tanpa iradiasi (LD50) dapat dihitung dicapai pada dosis 14.1 Gy. Respon yang serupa juga diperoleh pada inokulum tangkai daun (Y = 77. 1 1.2X - 0.04X2 , R2 = 0.87) (Gambar 2 B), dengan perbedaan bahwa LD50 dicapai pada dosis 19,5 Gy. Pada inokulum ruas batang, respon daya hidup terhadap dosis iradiasi terlihat berbeda tetapi sesuai dengan curvilinear model (Y = 51.9 4.2X +0.1X2, R2 = 0.98). Secara visual, pada inokulum ruas batang, respon daya
hidup menurun secara linear dari kontrol sampai dosis 12,5 Gy dan melandai pada dosis 25 Gy dan seterusnya (Gambar 2 C). Dengan respon seperti ini LD 50 diperkirakan dicapai pada dosis 5,5 Gy. Perbedaan LD50 antara inokulum yang berbeda menunjukkan perbedaan kepekaan jaringan untuk tumbuh setelah dipapar sinar gamma. Pengaruh dosis iradiasi sinar gamma terhadap morfogenesis berbagai inokulum kentang hitam in vitro. Iradiasi berpengaruh secara nyata terhadap morfogenesis dari ketiga inokulum yang diuji. Pada inokulum daun, kalus hanya terbentuk pada dosis irradiasi dari 0-12,5 Gy dengan kecenderungan respon curvilinear yang mencapai maksimum pada dosis 6 Gy (39%) dan menurun pada sampai 12.5 Gy, dan RD50 diperkirakan 22 Gy. Pada inokulum tangkai daun, respon pembentukan kalus menunjukkan kecenderungan curvilinear, yang dicirikan oleh peningkatan respon dari dosis 0 sampai dosis 6 Gy dan mencapai maksimun (39%) selanjutnya menurun pada dosis 12,5 Gy dan menurun dengan kemiringan yang lebih tajam pada dosis 25 Gy dan selanjutnya menurun lagi dengan kemiringan yang lebih landai pada dosis 35 Gy dan tanpa pembentukan kalus
Gambar 1. Inokulum kentang hitam yang berumur 3 minggu setelah disubkultur pada dosis iradiasi 0-6Gy (A), 12,5-25 Gy (B), 35-50 Gy (C)
171
Witjaksono &Leksonowati
pada 50 Gy. RD50 pembentukan kalus inokulum tangkai daun diperkirakan 24 Gy. Sedangkan pada inokulum ruas batang, respon pembentukan kalus sangat rendah dengan nilai maksimum sekitar 5% sehingga sukar dilihat kecenderungannya (Gambar 3 A). Respon persen pembentukan tunas dari inokulum daun dan tangkai daun menunjukkan respon curvilinear, dengan nilai maksimum respon yang lebih tinggi pada inokulum daun (Gambar 3 B). Nilai RD50 diperkirakan 12,5 Gy. Namun seperti halnya respon pembentukan kalus, respon pembentukan tunas dari inokulum ruas batang sangat rendah sehingga kecenderungan responnya sukar dipelajari (Gambar 3 B). Pada dosis 50
Gy, tunas sama sekali tidak terbentuk pada ketiga inokulum. Respon jumlah tunas per inokulum cenderung menurun linear dari dosis rendah ke dosis yang lebih tinggi untuk ketiga inokulum (Gambar 3 C). RD50 untuk respon ini diperkirakan tercapai pada dosis 8 Gy untuk inokulum daun dan 10 Gy untuk inokulum tangkai daun. Pertumbuhan tunas hasil regenerasi dari inokulum daun, tangkai daun dan ruas batang yang telah diiradiasi pada subkultur pertama (S1) Tinggi tunas pada medium pembesaran tunas dari tunas yang berasal dari inokulum daun masih terpengaruh oleh dosis iradiasi dan
100
100
60
80
80
50
60
60
40
40
40
30
20
20
20
0
0
10
0 0 20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 60
Dosis Radiasi (Gy)
Dosis iradiasi (Gy)
Dosis iradiasi (Gy)
Gambar 2. Respon curvilinear dari respon daya hidup terhadap dosis iradiasi dari inokulum daun (Y = 89.9 1.8x 0.1x2 , R2 = 0.95), tangkai daun (Y = 77.1 1.2X 0.04X2 , R2 = 0.87), dan ruas batang (Y = 51.9 4.2X + 0.1X2 , R2 = 0.98) umur 3 minggu.
Gambar 3. Pengaruh dosis iradiasi inokulum daun, tangkai daun dan ruas batang terhadap respon pembentukan kalus, pembentukan tunas dan jumlah tunas per inokulum yang terbentuk pada umur enam minggu setelah iradiasi.
172
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
menunjukkan respon curlinear seperti pada respon regenerasi (Gambar 4 A). Respon tinggi tunas dari tunas yang berasal dari inokulum tangkai daun menunjukkan kemiripan dengan respon tinggi tunas dari inokulum daun dengan perbedaan nilai antar dosis yang tidak nyata. Tinggi tunas dari inokulum ruas batang juga tidak menunjukkan respon nyata terhadap dosis iradiasi walaupun ada kecenderungan menurun (Gambar 4A). Perbedaan tinggi tanaman dari inokulum yang berbeda cenderung tidak nyata dan tidak menunjukkan pola yang jelas, walaupun pada beberapa dosis terjadi perbedaan yang nyata. Jumlah tunas yang terbentuk per inokulum tidak berbeda nyata dengan pertambahan dosis iradiasi. Perbedaan jumlah tunas yang terbentuk per inokulum juga tidak berbeda antar asal inokulum (Gambar 4B). Jumlah tunas per inokulum mencapai rata-rata 6 tunas. Pengaruh dosis iradiasi terhadap morfologi kentang hitam hasil iradiasi Dosis iradiasi tidak hanya berpengaruh terhadap respon
morfogenesis dari inokulum daun, tangkai daun dan ruas batang, tetapi juga berpengaruh pada morfologi dari biak yang dihasilkannya. Perubahan yang teridentifikasi antara lain morfologi daun yang menjadi tidak normal. Selain itu, daun albino pada helaiannya (Gambar 5 A), maupun pada tepiannya sehingga menyerupai variegata (Gambar 5 B ) juga teramati. Perbedaan bentuk daun yang teramati anatara lain ujung meruncing (Gambar 5 C). Pada dosis 12.5 dan 25 Gy banyak biak yang diperoleh berbentuk roset, dengan buku sangat rapat dengan jumlah tunas yang banyak pada satu inokulum (Gambar 5 D). Biak yang tumbuh dari hasil iradiasi ini juga banyak yang mengalami gejala hiperhydricity atau menggelas. Aklimatisasi, trasplanting dan morfologi mutan di lapang. Banyaknya tanaman yang diaklimatisasi di greenhouse cenderung meningkat dari kontrol tanpa iradiasi ke dosis iradiasi 6 Gy lalu menurun lagi sampai dosis iradiasi 35 Gy (Tabel 1). Kecenderungan ini teramati pada semua inokulum yang diamati, walaupun pada
Gambar 4. Pertumbuhan tunas setelah disubkultur sekali (S1) yang berasal dari inokulum kentang hitam yang diiradiasi. A) tinggi tanaman (cm) dan B) jumlah tunas.
173
Witjaksono &Leksonowati
Gambar 5. Pengaruh dosis iradiasi terhadap morfologi biak tunas hasil regenerasi. A) albino (12.5 Gy), B) variegata (25 Gy), C) bentuk daun meruncing (25 Gy), D) kerdil (25 dan 35 Gy).
inokulum yang berbeda jumlah tunas yang diaklimatisasi berbeda dan tangkai daun menunjukkan jumlah yang tertinggi (Tabel 1). Pada saat diaklimatisasi, morfologi daun dari tanaman yang berasal dari perlakuan iradiasi yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan, kecuali pertumbuhan. Pertumbuhan yang paling bagus terdapat pada dosis 6 Gy dan menurun pada dosis 12.5 Gy dan 25 Gy (kerdil). Jumlah tanaman yang bertahan tumbuh di polibag juga mempunyai pola yang sama dengan pertumbuhan bibit diaklimatisasi. (Tabel 1). Sejumlah tanaman hasil iradiasi dan tanpa irradiasi telah ditanam di lahan (Tabel 2). Variasi morfologi ukuran daun maupun pertumbuhan terlihat diantara aksesi dan karena itu aksesi tanaman yang menunjukkan morfologi yang berbeda disimpulkan sebagai mutan. Tanaman yang diperoleh dari perlakuan irradiasi 6 Gy tidak menunjukkan perbedaan morfologi yang nyata dibanding kontrol, bahkan cenderung 174
tumbuh lebih subur. Namun tanaman yang diperoleh dari perlakuan iradiasi yang lebih tinggi menunjukkan variasi pigmentasi daun, menjadi lebih pendek, daun lebih meruncing, daun bertumpuk. Selain itu juga diperoleh mutan yang menunjukkan pembungaan yang lebih awal (Gambar 6 B) dari kontrol tanpa perlakuan iradiasi (Gambar 6 A) PEMBAHASAN Kentang hitam adalah tanaman yang membiak secara vegetatif dan secara alamiah steril dan karena itu keragaman genetiknya diperkirakan sempit. Perbaikan tanaman ini, karena itu, memerlukan induksi keragaman genetik secara buatan seperti induksi mutasi. Protokol induksi mutasi pada kentang hitam telah berhasil kami kembangkan dan laporkan pada makalah ini dengan mengambil manfaat kemampuan kentang hitam diregenerasi secara
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
Tabel 1. Jumlah bibit kentang hitam klon Nganjuk 1 dari perlakuan iradiasi yang hidup pada tahap aklimatisasi dan transplantingInokulum asal Irradiasi (Gy) Daun 0 6 12.5 25 35 0 6 12.5 25 35 0 Jumlah bibit aklimatisasi 15 24 14 0 34 27 96 58 10 0 34 Jumlah bibit transplant (polibag) 9 64 9 1 22 8 21 21 1 0 24 Jumlah bibit total 26 88 23 3 56 35 117 79 11 0
Tangkai Daun
58 6 62 19 81 12.5 5 2 7 0 2 2 25 35 28 6 34 Keterangan: data tanaman yang diaklimatisasi dan ditransplanting mencakup keseluruhan tanaman Batang
Ruas
Tabel 2. Kentang hitam klon Nganjuk 1 hasil induksi mutasi yang ditanam di lapangan. Perlakuan Inokulum Daun Daun Batang Batang Tangkai daun Tangkai daun Tangkai daun Dosis iradiasi 6 Gy 12.5 Gy 0 Gy 12.5 Gy 0 Gy 6 Gy 25 Gy Jumlah tanaman di lapang 22 6 8 2 2 6 3
langsung dari inokulum daun, tangkai daun ruas batang dari biak tunas in vitro (Leksonowati & Witjaksono 2012). Induksi mutasi secara in vitro menghemat tempat dan waktu karena dalam kultur in vitro, pertumbuhan cepat dan ukuran kecil. Abraham & Rajakhrisnan (2009) melaporkan keragaman ukuran dan
produksi umbi dari mutan yang diperoleh dari iradiasi ruas batang dengan satu buku. Teknik yang dipakai seharusnya mensyaratkan beberapa kali penyetekan untuk menghilangkan kimera yang mungkin terjadi, tetapi hal ini tidak dijelaskan dalam makalah tersebut.
175
Witjaksono &Leksonowati
A
B
Gambar 6. Pertumbuhan dan morfologi tanaman kentang hitam di lapang hasil regenerasi perlakuan iradiasi sinar dari inokulum tangkai daun. A) kontrol, 0 Gy, B) tanaman berbunga lebih awal, 25 Gy.
Respon pertumbuhan (persen daya tumbuh, pembentukan kalus maupun pembentukan tunas) terhadap dosisi iradiasi pada kentang hitam cenderung bersifat curvilinear yaitu meningkat pada dosis rendah dan kemudian menurun pada dosis tinggi dan dengan koefisien korelasi yang lebih tinggi (87-98%). Pola respon terhadap dosis iradiasi yang curvilinear juga dilaporkan pada apokat (Fuentes et al. 2009), dan talas (Colocasia esculenta) (Seetohul et al. 2009). Iradiasi pada dosis tinggi menyebabkan kematian pada sel atau jaringan sedangkan iradiasi pada dosis rendah justru memicu pertumbuhan sel. Iradiasi pengion dosis tinggi dapat mengakibatkan kerusakan sel karena adanya gangguan pada molekul air, DNA, enzim dan zat pengatur tumbuh dalam sel (Handro 1981). Perbedaan respon antara inokulum dan bahwa daun dan tangkai daun menunjukkan respon regenerasi yang lebih baik dari ruas batang sesuai dengan kapasitas regenerasi dari inokulum tersebut menurut penelitian sebelumnya tentang organogenesis kentang hitam (Leksonowati & Witjaksono 2012) dan dengan demikian irradiasi tidak merubah 176
kapasitas regenerasi dari suatu jaringan. Iradiasi telah ditunjukkan dapat meningkatkan kemampuan regenerasi. Pada kultur kalus Anthurium andreanum, pemberian dosis iradiasi sebesar 100 RAD dapat merangsang pembentukan tunas (Pierik 1987). Sedangkan pemberian dosis iradiasi sebesar 500 RAD secara nyata merangsang pembentukan tunas dari eksplan tanaman gerbera (Prasetyorini 1991). Pada dosis iradiasi yang diuji, respon pertumbuhan 50% dicapai pada dosis yang berbeda-beda, antara 5.5 sampai 19,5 Gy untuk daya hidup, 22-24 Gy untuk pembentukan kalus dan antara 6-12,5 Gy untuk pembentukan tunas. Karena regenerasi tunas mutan yang menjadi tujuan, maka pemilihan dosis radiasi selayaknya menggunakan peubah regenerasi tunas. Karena antara dosis iradiasi 6 Gy sampai 35 Gy dihasilkan tunas, walaupun dosis respon pembentukan tunas sebanyak 50% jatuh pada dosis sekitar 12,5 Gy, maka percobaan iradiasi seharusnya tidak hanya mengikuti dosis RD50. Dosis yang lebih rendah atau lebih tinggi dari RD50 perlu dimanfaatkan. Penanaman di
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
lapang terhadap tanaman hasil iradiasi dibandingkan kontrol menunjukkan perbedaan morfologi pada tanaman dari perlakuan iradiasi dosis 12,5-25 Gy. Karena itu dosis 12,5-25 Gy dapat direkomendasikan sebagai dosis perlakuan iradiasi pada kentang hitam. Iradiasi sinar J dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil sehingga daun menjadi albino atau variegata. Hal ini juga dijumpai pada kentang hitam. Adanya variasi klorofil tersebut kemungkinan karena adanya mutasi yang mengakibatkan gangguan fisiologi dalam sintetis klorofil sehingga terjadi defisiensi klorofil pada daun. Adanya variasi klorofil tersebut kemungkinan karena adanya mutasi yang mengakibatkan gangguan fisiologi dalam sintetis klorofil sehingga terjadi defisiensi klorofil pada daun (Grosch &n Hopwood 1979). Banerji et al. (1987) melaporkan bahwa persentase tertinggi dari tanaman yang berdaun variegata diperoleh pada perlakuan 7.5 Gy dimana variasi penyebaran klorofil terlihat di bagian tertentu pada daun atau keseluruhan daun. Sedangkan persentase daun abnormal tertinggi diperoleh pada perlakuan 10 Gy. Tanaman yang diiradiasi juga umumnya menghasilkan penyimpangan pada daun termasuk kekerdilan, penebalan, perubahan bentuk dan tekstur, kerutan, lekukan yang abnormal, keriting pada pinggiran daun, perubahan bentuk tulang daun, fusi dan perubahan warna daun. Protokol yang dikembangkan sangat sederhana dan meliputi penumbuhan biak in vitro pada medium MS dengan konsentrasi BA dan NAA rendah. Biak tunas pada pertumbuhan maksimum
yang telah berumur 5-6 minggu dan masih dalam botol mediumnya diiradiasi dengan sinar gamma pada dosis 12,5-35 Gy. Paling lambat sehari kemudian, dari biak yang diiradiasi diambil daun dan tangkai daun dan ditumbuhkan pada medium regenerasi yang berisi medium MS ditambah 5 mg/l BA dan 0,1 mg/l NAA selama 6 minggu. Tunas yang tumbuh kemudian disubkultur pada medium MS tanpa zat pengatur tumbuh untuk pembesaran tunas. Tunas kemudian diaklimatisasi dan dibesarkan pada medium tanah dalam polibag. Tanaman putative mutan telah ditanam di lahan dan menunjukkan keragaman genetik seperti pembungaan lebih awal. KESIMPULAN Iradiasi pada dosis 6-35 Gy pada biak tunas diikuti regenerasi dari inokulum daun, tangkai daun dan ruas batang efektif dalam menghasilkan mutant misalnya dengan karakter pembungaan lebih awal serta morfologi daun yang berbeda. Teknik iradiasi dan regenerasi yang dikembangkan terbukti efektif dalam menginduksi keragaman genetik pada kentang hitam. UCAPAN TERIMA KASIH Penelitian ini didanai dari DIPA 2008-2010 Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Katarina Utami Nugraheni, S.P., Yudhisa, Nenah, Enjut, Omi, Biah dan almarhumah Nur atas bantuan teknis selama penelitian.
177
Witjaksono &Leksonowati
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, TL., J. Endan, BM. Nazir. 2009. Changes in Flower Development, Chlorophyll Mutation and Alteration in Plant Morphology of Curcuma alismatifolia by gamma irradiation. Amer.J.Appl. Sci. 6(7): 1436-1439. Abraham M & VV Radhakrishna. 2009. Induced Mutations in Coleus (Solenostemon rotundifolius) (Poir. J.K. Mortan) An UnderUtilized Medicinal Tuber. In: Q.Y. Shu (ed.), Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p 283-285 Anonymous. 1970. Manual on Mutation Breeding. Technical Reports Series No. 119. International Atomic Energy Agency, IAEA, Vienna. Banerji, BK., P. Nath & SK. Datta. 1987. Mutation breeding in double bracted Bougainvillea cv. Rosevilles Delight. J. Nuclear Agric. Biol. 16:45-47. Fuentes, JL., L. Santiago, NN. Rodrguez, OC. Arbelo, A. Alvarez, Y. Valds1, M. Vernhe1, M. Guerra1, S. Altanez, EF. Prieto, B. Velzquez, JA. Rodrguez, DG. Sourd, VR. Fuentes & MR. Leal. 2009. Combining zygotic embryo culture and mutation induction to improve salinity tolerance in avocado (Persea americana Mill). Induced Mutation in Tropical Fruit Tree. IAEA Tecdoc 1615. International 178
Atomic Energy Agency, May 2009. Pp.71-82. (http: //mvgs.iaea.org/ pdf/TECDOC1615.pdf) Grosch, DS. & LE. Hopwood. 1979. Biological Effect of Radiation. Second edition. London: Academic Press. Heyne, H. 1987. Tumbuhan berguna Indonesia. Balitbang Kehutanan. Departemen Kehutanan RI. Jakarta Handro, W. 1981. Mutagenesis and in vitro Selection. In. Thorpe TA (ed). Plant Tissue Culture, Methods and Application in Agriculture. New York: Academic Press. Hoesen, DSH. 1991. Biak jaringan kentang hitam (Coleus tuberosus Benth.) Dalam: Witjaksono, Marwoto RM & Supardiyono EK (eds.) Prosiding Seminar hasil Penelitian dan pengembangan Sumberdaya hayati 1990/1991. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi, LIPI. Bogor, 99-104. Jansen, PCM. 1996. Plectranthus rotundifolius (Poiret) Sprengel. In: Flach, M. & F. Rumawas (eds.). Plant yielding non-seed Carbohydrates. PROSEA, Bogor, 141-143. Leksonowati, A. & Witjaksono. 2012. Morfogenesis pada daun, tangkai daun, dan ruas batang kentang hitam (Solenostemon rotundifolius (poir) JK Morton) secara in vitro. Berkala Penelitian Hayati (in press). Murashige, T. & Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue
Iradiasi Sinar J pada Biak Tunas Kentang Hitam
culture. Physiol Plants. 15: 473497. Pierik, RLM. 1987. In Vitro Culture of Higher Plants. Neterland: Martinus Nijhoff Publishers Prasetyorini. 1991. Pengaruh radiasi sinar gamma dan jenis eksplan terhadap keragaman somaklonal pada tanaman gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook) [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pascasarjana. Prematilake, DP. 2005. Inducing genetic variation of innala (Solanostemon rotundifolius) via in vitro callus culture. J. Natn. Sci. Found. Sri Lanka 33: 23-131. Poerba, YS. 2004. Penampilan genotipe som jawa [Talinum paniculatum Jacq. (Gaertn.)] pada generasi M2. Berita Biologi 7(3). 127-135. Seetohul S., V. Maunkee & M. Gungadurdoss. 2009. Improvement of Taro (Colocasia esculenta var esculenta) through In Vitro
Mutagenesis. In: QY. Shu (ed.), Induced Plant Mutations in the Genomics Era. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p 296-299 Soedjono, S. 2003. Aplikasi mutasi induksi dari variasi somaklonal dalam pemuliaan tanaman. J. Litbang Pertanian. 22(2): 70-78. Suherlina, T., A. Leksonowati & Witjaksono 2012.Pengaruh umur biak dan posisi daun kentang hitam (Solenostenon rotundifolius (Poir) JK Morton) in vitro.Berkala Penelitian Hayati (Submitted) Vimala, B. & B. Nabisan. 2005. Tropical Minor Tuber Crops. Central Tuber Crops Research Institute Sreekariyam, Thiruvananthapuram 695 017, Kerala, India. 24p. Witjaksono & RE. Litz. 2004. Effect of gamma irradiation of avocado embryogenic cultures and somatic embryo recovery. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 77:139-147
Memasukkan: Agustus 2011 Diterima: Januari 2012
179
Jurnal Biologi Indonesia 8(1): 181-196 (2012)
Persilangan Pisang Liar Diploid Musa acuminata Colla var malaccensis (RIDL.) Nasution Sebagai Sumber Polen dengan Pisang Madu TetraploidYuyu S. Poerba*, Fajarudin Ahmad* & Witjaksono**Pusat Penelitian Biologi LIPI, **)Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong Science Center. Jalan Raya Jakarta- Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911 ABSTRACT Hybridization of wild diploid Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution as pollen source with teraploid Pisang Madu. Indonesia and South East Asia is the center of origin and genetic variability of bananas, specifically species Musa acuminata Colla. At least 15 varieties of wild Musa acuminata are found in Indonesia. Some of them have resistances for several diseases of bananas. One approach in banana breeding program is hybridizing between tetraploid parent and diploid parent of banana. This research was aimed to produce new triploid banana hybrid by crosses between tetraploid female parent Pisang Madu and wild diploid male parent Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution. From 302 crosses, 53.9% of crosses produced seeds. However, only 48.46% of seeds contained embryos, and only 1.27% of embryos grew and developed. Bunch weight and leaf length of hybrid plants were not significantly different with female parent, tetraploid Pisang Madu. Plant height of the hybrids was not significantly different with male parent, wild diploid Musa acuminata var malaccensis. Pseudostem diameter and leaf width of the hybrid plants were between female tetraploid parent and male wild diploid parent. RAPD profiles (DNA bands) of the hybrids were originated from the female parent, male parent and both parents were 38.46, 34.6, and 26.92%, respectively. The hybrids were confirmed to be triploids (3x=33). Keywords: banana, breeding, hybrids, tetraploid, wild diploid, Pisang Madu, Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution*)
PENDAHULUAN Indonesia dan Asia Tenggara merupakan pusat keragaman pisang (Musaceae) yang tersebar hampir di seluruh Indonesia (Nasution 1991). Lebih dari dua ratus varietas ditanam oleh petani yang seluruhnya adalah varietas alami yang belum mengalami perbaikan/pemuliaan. Selain itu, terdapat paling sedikit 15 varietas liar berbiji Musa acuminata Colla (Nasution 1991) sangat bervariasi dari karakter ukuran buah hingga morfologi biji. Keanekara-
gaman plasma nutfah pisang ini dapat digunakan sebagai sumber daya genetik untuk pemuliaan pisang. Indonesia juga merupakan sumber keragaman genetik patogen pisang yang meliputi penyakit Panama atau layu Fusarium (patogen: Fusarium oxysporum var. cubesence), Sigatoka (patogen: Mycospaerella musicola), Pseudomonas sp., nematoda, dan virus (Banana Bunchy Top Virus/ BBTV, Banana Streak Virus/BSV, Cucumber Mosaic Virus/BMV dan Banana Bract Mosaic Virus/BBrMV).
181
Poerba dkk.
Varietas pisang yang dibudidayakan masyarakat telah banyak mengalami tekanan lingkungan terutama penyakit layu Fusarium. Usaha penanaman pisang varietas Cavendish atau varietas lain seperti Raja (AAB), Ambon Lumut (AAA), Barangan (AAA) dalam sistem monokultur pada areal yang agak luas seringkali menemui kehancuran akibat penyakit layu Fusarium, walaupun varietas-varietas ini bertahan hidup dalam rumpun-rumpun yang terpisah. Pengendalian penyakit ini secara kimia tidak efektif karena sifat patogen yang tular tanah. Salah satu cara untuk pengendalian penyakit ini adalah dengan menggunakan varietas pisang tahan penyakit layu Fusarium. Hibrid triploid tahan penyakit menjadi target pemuliaan pisang karena triploid mempunyai vigor dan produktifitas paling baik. Hibrid triploid tahan Fusarium dapat diperoleh dengan persilangan antara tetua betina tetraploid dan jantan diploid (Stover & Buddenhagen 1986), dengan sifat ketahanan penyakit dimasukkan dari tetua jantan diploid sebagai sumber polen kedalam hibrid triploid baru (Stover & Simmonds 1987). Pendekatan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan tetua betina tetraploid dengan tetua jantan diploid pisang liar dan budidaya hibrid telah diperoleh dengan frekuensi yang bervariasi dari 30-88% (Ortiz et al. 1998a) dan 3.8%-94.1% (Osebele et al. 2006a), tergantung tetua yang digunakan (Ortiz et al. 1998a; Osebele et al. 2006a, Ortiz 1997, Ortiz & Vuylsteke 1995). Pemilihan tetua jantan sangat kritikal dan sangat menentukan dalam strategi 182
untuk menghasilkan hybrid triploid (Osebele et al. 2006). Selain harus memiliki fertilitas polen yang tinggi, tetua jantan biasanya digunakan sebagai sumber ketahanan hama/penyakit (Ortiz et al. 1998b). Pisang liar memiliki fertilitas polen dan viabilitas polen yang lebih tinggi dibandingkan dengan pisang domestikasi/budidaya (Dumple & Ortiz, 1996; Ortiz et al. 1998b), dan biasanya memiliki sumber ketahanan terhadap penyakit sangat menguntungkan digunakan sebagai tetua jantan (Ortiz et al. 1998b). Penelitiannya Ortiz et al. (1998b) menunjukkan bahwa pisang diploid liar, Calcutta 4 (Musa acuminata ssp burmacoides) memiliki viabilitas dan fertilitas polen yang lebih tinggi dibandingkan dengan pisang diploid domestikasi (Pisang Lilin, Galeo) dan pisang hibrid diploid banana-plantain (TMP2x 1297-3). Oleh karena itu, pada penelitian ini, pemanfaatan tetua jantan liar Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution sebagai sumber polen yang mempunyai sifat ketahanan terhadap Fusarium, digunakan dalam pemuliaan pisang triploid tahan Fusarium. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hibrid pisang triploid baru melalui persilangan tetua betina pisang madu tetraploid hasil induksi dengan tetua diploid pisang liar Musa acuminata var malaccensis. BAHAN DAN CARA KERJA Pisang Madu tetraploid (AAAA) hasil induksi poliploidi digunakan sebagai tetua betina untuk diserbuki dengan
Persilangan Pisang Liar Diploid Musa acuminata
serbuk sari dari tetua jantan diploid, pi sang l i ar Musa acuminata var malaccesensis (AA wild). Pisang madu tetraploid memiliki keunggulan sebagai berikut: diameter buah yang lebih besar dibandingkan dengan diploidnya, rasa buah manis, tangkai buah tidak mudah rontok, kulit buah tidak menempel pada daging buah. Sedangkan tetua jantan, Musa acuminata var malaccensis diploid (AA wild) merupakan pisang liar berbiji, tahan terhadap penyakit penyakit layu Fusarium. Sejumlah 302 persilangan dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari pisang liar M. acuminata var malaccensis dan menyerbukkannya pada bunga betina Pisang Madu tetraploid. Penyerbukan dilakukan pada pagi hari antara jam 810, pada saat putik receptive dan serbuk sari matang. Setelah penyerbukan, tandan bunga ditutup dengan jaring halus untuk mencegah penyerbukan silang oleh serangga atau penyerbuk lainnya. Buah hasil persilangan dipanen pada saat buah masak fisiologis. Sejumlah 163 biji hasil persilangan diekstrak dari buah yang sudah masak penuh dan lunak dan diberi label sesuai persilangannya. Selanjutnya biji diselamatkan dengan teknik embryo rescue. Biji yang telah dipilih didisinfestasi dengan larutan Bayclin 20% selama 1020 menit dan dibilas akuades steril 2x dalam laminar air flow cabinet. Setelah dikeringkan, biji diiris longitudinal pada sisi sebelah mikrofil. Embrio yang berwarna putih opak diambil dengan ujung skalpel dan di letakkan pada permukaan medium tumbuh. Medium tumbuh berisi garam formulasi MS
(Murashige & Skoog 1962), 30 g l-1 gula, 100 mg l-1 myo inositol, 4 mg l-1 thiamine HCl dengan tambahan 2 mg/l BA. Biak tunas yang telah berhasil diiniasisi dipelihara dan diperbanyak dengan subkultur 1-3 bulan pada medium garam formulasi MS (Murashige dan Skoog, 1962), 30 g l-1 gula, 100 mg l-1 myo inositol, 4 mg l-1 thiamine HCl dan 2 mg l -1 BA dan dipadatkan dengan 8 g/l agar. Setelah tunas bertumbuh menjadi plantlet, selanjutnya diaklimatisasi di rumah kaca. Aklimatisasi dilakukan dengan mengadaptasikan biak tunas pisang dari kondisi in vitro dengan kelembahan tinggi dan intensitas cahaya rendah ke kondisi ex vitro dengan kelembaban rendah dan intensitas cahaya tinggi dalam dua tahap. Pada tahap pertama tunas di tanam dalam bak plastik yang diisi medium tumbuh pasir, tanah dan cocopeat steril dan dengan perbandingan 2:1:2 ditutup rapat dengan plastik dan dipelihara di bawah naungan 50-75%. Setelah 1 bulan dan daun baru tumbuh dan akar telah beregenerasi, bibit dipindah pada medium tanah dalam polibag dan dipelihara dengan naungan 25-50% selama 2-3 bulan dan selanjutnya naungan dibuka sepenuhnya selama sebulan sebelum bibit dapat di tanam di lapang. Hibrid yang sudah ditanam di lapang diamati perkembangannya. Data-data pertumbuhan dan reproduksi, data morfologi dilakukan sesuai dengan Descriptors for Banana (Musa spp.) (IPGRI-INIBAP/CIRAD 1996). Untuk membandingkan penampilan tanaman hibrid dengan tetuanya, beberapa karakter agronomis seperti 183
Poerba dkk.
bobot tandan, tinggi tanaman, diameter batang, panjang dan lebar daun, serta panjang tandan diamati. Analisis statistik dilakukan dengan Uji-T (Steel &Torrie, 1980). Hibrid hasil persilangan diidentifikasi secara molekuler dengan menggunakan marka Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Ekstraksi DNA genom dilakukan dengan metoda CTAB (Delaporta et al., 1983) yang sudah dimodifikasi. Analisis RAPD dilakukan dengan metoda metoda Williams et al (1990). Amplifikasi DNA dilakukan dengan Thermal Cycler (Takara) dengan kondisi amplifikasi sebagai berikut: Amplifikasi DNA dilakukan berdasarkan metode Williams et al. (1990) dengan menggunakan lima primer RAPD terpilih, yaitu OPA-18, OPA-13, OPD-08 OPN06 dan OPN-12 (Operon Technology Ltd). Reaksi PCR dilakukan pada volume total 15 Pl yang berisi 0.2 nM dNTPs; 1X bufer reaksi; 2mM MgCl2; 25 ng DNA sample; 1 pmole primer tunggal; dan 1 unit Taq DNA polymerase (Promega) dengan menggunakan Thermocylcer (Takara) selama 45 siklus. Pemanasan pertama pada suhu 94 0C selama 2 menit, kemudian diikuti oleh 45 siklus yang terdiri atas denaturasi 1 menit pada suhu 940C, annealing 1 menit pada suhu 360C, dan 2 menit ektensi pada suhu 720C. Setelah 45 siklus selesai, kemudian diikuti 5 menit proses ekstensi fragmen DNA pada suhu 720C dan pendinginan pada suhu 250C. Hasil amplifikasi PCR divisualisasi pada gel agarosa 2.0% dalam bufer TAE (Tris-EDTA) secara elektroforesis dengan menggunakan Mupid Mini Cell selama 50 menit pada 184
50 Volt. Kemudian direndam dalam larutan ethidium bromida dengan konsentrasi akhir 1Pl/100 ml selama 10 menit. Hasil pemisahan fragmen DNA dideteksi dengan menggunakan UV transluminator, kemudian difoto dengan menggunakan geldoc (Takara). Sebagai standar ukuran DNA digunakan 100 bp plus DNA ladder (Fermentas) untuk menetapkan ukuran pita hasil amplifikasi DNA. Analisa ploidi 13 sampel hibrid, tiga sampel tetua betina, dan tiga sampel tetua jantan menggunakan larutan Cystain UVploidy (Partec, Germany) yang berisi buffer dan pewarna DNA. Potongan daun berukuran sekitar 100 cm2 diambil dari tanaman di kebun, diberi label dan disimpan di wadah plastik. Di antara daun diselipkan kertas tissue yang dibasahi dengan aquades. Potongan daun berukuran 0,5 cm2 diletakkan di petridish dan ditetesi 1,5 ml buffer cystain UVPloidi (Partec, Germany) dan dicacah dengan silet. Cacahan daun disaring dengan saringan 30 m dan filtrat di masukkan dalam tabung cuvette untuk analisa. Sampel dibaca pada panjang gelombang 440 nm dan kecepatan 1000 nuclei per detik. Jumlah DNA pada inti sel sampel kontrol tanaman diploid dikalibrasi pada channel 200. Data ditunjukkan dalam bentuk grafik. Tanaman diploid menunjukkan peak pada channel 200, triploid pada channel 300 dan tetraploid pada channel 400, dan tanaman mixoploid menunjukkan lebih dari 1 peak pada channel yang berbeda. Rata-rata kandungan DNA (mean) dan coefficient of variation (CV) dari tiaptiap sampel pada setiap peak diamati dan
Persilangan Pisang Liar Diploid Musa acuminata
dibandingkan dengan tanaman kontrol, dan ditentukan tingkat ploidinya sesuai dengan kelipatan rata-rata jumlah kandungan DNA. HASIL Persilangan pisang Madu tetraploid dengan Musa acuminata var malaccensis diploid Dari 302 persilangan yang dilakukan dihasilkan 163 biji (53.97%) (Tabel 1). Namun demikian, dari 163 biji hibrid pisang hanya 79 (48.46%) saja yang mengandung embrio. Dengan teknik kultur embrio, ke-79 embrio ini kemudian diselamatkan. Walaupun demikian, tidak semua embrio dapat hidup dan bertumbuh, dan hanya satu embrio (1.27%) saja yang hidup dan bertunas.
Dari satu genotip embrio hibrid pisang yang bertunas, kemudian diperbanyak secara in vitro, kemudian diaklimatisasi dan ditanam di lapang. Penampilan morfologi tanaman pisang hibrid Dari pengamatan penampilan (habitus tanaman), hibrid pisang mempunyai habitus merunduk (Gambar 1b) yang menunjukkan morfologi pisang poliploid, yang dicirikan dengan menjuntainya pelepah daun. Penampilan tanaman (habitus tanaman) yang merunduk ini lebih menyerupai tetua betina Pisang Madu tetraploid (Gambar 1a), dibandingkan dengan tetua jantan diploid Musa acuminata var malaccensis yang memliki habitus tegak (Gambar1c).
Tabel 1. Persilangan Pisang Madu tetraploid dengan pisang liar diploid Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution.Nomor Persilangan Jumlah Persilangan Jumlah biji Jumlah embrio embrio yang bertunas
I 8A#4(2) x II 17B#3 I 8A#4(3) x II 17B#3 I 8A#4(4) x II 17B#3 I 8A#4(5) x II 17B#2 I 8A#4(6) x I 20B#3 I 8A#4(7) x I 20B#3 I 8A#4(8) x I 17B#3 I 8A#2(1) x II 17B#4 I 8A#2(2) x II 17B#4 I 8A#5(1) x I 20B#4 I 8A#5(2) x I 20B#5 I 8A#5(3) x I 20B#6 I 8A#5(4) x I 20B#4 I 8A#5(5) x I 20B#4 I 8A#5(6) x I 20B#4 Jumlah
22 21 21 21 21 21 18 27 29 22 21 17 17 17 7 302
16 9 52 40 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
10 5 22 19 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
185
Poerba dkk.
Pseudostem (batang semu) berbentuk silinder dengan tinggi mencapai 2,40 m, berwarna hijau kekuningan. Warna yang dominan pada bagian bawah pseudostem adalah hijau kekuningan dengan warna pigmentasi merah muda (Gambar 2B1). Getah pseudostem keruh seperti susu, lebih menyerupai tetua betinanya dibandingkan dengan tetua jantan yang memiliki getah jernih seperti air (Gambar 2C2). Lapisan lilin pada lembaran daun sangat sedikit seperti kedua tetuanya (Gambar 2A3,2C3). Permukaan daun bagian atas berwarna hijau lebih terang dibandingkan dengan tetua betina yang berwarna hijau gelap, dan lebih terang dibandingkan dengan tetua betina yang hijau agak suram, sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda (Gambar 2A3, 2B3, 2C3). Bagian kiri dan kanan pangkal daun berukuran tidak sama (asimetris) dengan bentuk yang membulat lebih menyerupai tetua jantannya (Gambar 2A3, 2B3, 2C3). Bagian pangkal dari tangkai daun mempunyai ornamen bercak berwarna cokelat seperti kedua tetuanya (Gambar 2A4,2B4,2C4). Tipe lekuk tangkai daun (petiole canal) pada daun ketiga tanaman hibrid terbuka dengan tepi berombak, yang lebih menyerupai tetua betinanya, dibandingkan dengan tetua jantan yang memiliki tipe lebar dengan tepi tegak (Gambar 2A5, 2B5,2C5). Bentuk male bud (jantung) hibrid intermediate dari kedua tetua(ovoid-tetua betina, seperti gasing-tetua jantan). Braktea akan menggulung sebelum jatuh,
seperti kedua tetuanya (Gambar 2A6, 2B6, 2C6). Tandan buah dengan total panjang (peduncle) 43-46 cm. Posisi bunch (tandan buah) miring merupakan bentuk intermediate dari kedua tetuanya. Susunan buah biseriate (buah tersusun dalam dua baris) seperti kedua tetuanya (Gambar 3), ukuran buah lebih panjang dan diameter buah lebih kecil dibandingkan kedua tetuanya (Gambar 3). Penampilan tanaman dan morfologi tanaman pisang hibrid dan kedua tetuanya disarikan pada Tabel 2. Karakter Agronomis Hibrid Hasil uji T lima karakter agronomis tetua persilangan dan hibridnya tertera pada Tabel 3. Bobot tandan dan panjang daun hibrid tidak berbeda nyata dengan tetua betina, Pisang Madu tetraploid, tetapi sangat berbeda nyata dengan tetua jantannya, Musa acuminata var malaccensis. Tinggi tanaman pisang hibrid berbeda nyata dengan tetua betina, tetapi tidak berbeda nyata dengan tetua jantannya. Sedangkan pada karakter diameter batang dan lebar daun tanaman hibrid sangat berbeda nyata dengan kedua tetuanya. Analisis hibrid pisang dengan marka RAPD (randomly amplified polymorphic DNA) Identifikasi molekuler hibrid dilakukan dengan menggunakan empat primer RAPD, yaitu OPA-07, OPA-13, OPB -07, dan OPB-18. Untuk setiap primer dan hibrid, analisis RAPD dilakukan untuk mengkarakterisasi pola pita DNA (Chundet et al., 2007). Pola
186
Persilangan Pisang Liar Diploid Musa acuminata
a
b
c
Gambar 1. Penampilan tanaman pisang madu tetraploid (a), hibrid (b) dan Musa acuminata Colla var malaccensis (Ridl.) Nasution (c)A1 B1 C1 A4 B4 C4
A2
B2
C2
A5
B5
C5
A3
B3
C3
A6
B6
C6
Gambar 2. Penampilan morfologi Pisang Madu Tetraploid (A), hibrid (B) dan Musa acuminata var malaccensis (C). Ket: 1. Batang bagian dalam, 2 Getah, 3. Pangkal lamina, 4. Bercak, 5. Petiol canal, 6. Jantung
Gambar 3. Penampilan tandan dan buah pisang hibrid (B) dibandingkan dengan kedua tetuanya: Pisang Madu Tetraploid (A) dan Musa acuminata var malaccensis (C)
187
Poerba dkk.
Tabel 2. Perbandingan karakter morfologi pisang hibrid dengan kedua tetuanya
Sub no.
Karakter
Pisang Madu 4x (Tetua ? ) Merunduk 237-285 19.4-25.5 Kekar Hijau muda Merah muda-ungu 7+1 225+34 71+4 3+0.3 41+8 Hijau muda (lebih tua dp diploidnya) Hijau muda (lebih tua dp diploidnya) 5+0.5 38+1 Tergantung vertikal Paralel terhadap ibu tangkai >17 10+0.9 2.6+0.2 Tumpul Terdapat pangkal sisa putik 14 8.51.5 1.90.2 Tumpul Terdapat pangkal sisa putik 17 111.6 2.80.8 Tumpul Terdapat pangkal sisa putik

![[XLS]eci.nic.ineci.nic.in/delim/paper1to7/TamilNadu.xls · Web viewRev. Dharmapuri & Kanniyakumari Paper 7 Paper 6 Paper 5 Paper 4 Paper 3 Paper 2 Paper 1 Index Tirunelveli (M.Corp.)](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5ad236e17f8b9a86158ce167/xlsecinicinecinicindelimpaper1to7-viewrev-dharmapuri-kanniyakumari-paper.jpg)