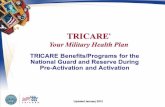51Yuni Tri
-
Upload
joanne-lee -
Category
Documents
-
view
94 -
download
2
Transcript of 51Yuni Tri
PEMAHAMAN MURID SEKOLAH DASAR TERHADAP KONSEP IPA BERBASIS BIOLOGI: SUATU DIAGNOSIS ADANYA MISKONSEPSIYuni Tri Hewindati Adi SuryantoThis article is based on a research aim in finding out primary school pupils conceptions on natural sciences from the biological view points, identifying the presence of pupils misconceptions, and identifying factors affecting the pupils misconception based on their responses. Conducted in West Java, Daerah Istimewa Yogyakarta, and East Java, sample of this research consisted of 186 pupils grade five from 12 elementary schools which were selected by purposive random sampling. Data were collected by interviews. Findings of this research revealed that misconception occured in all concepts which were investigated. Based on the results, it is suggested that elementary school science teachers should improve their teaching and learning process in order to provide pupils with right concepts of natural sciences. Key words: misconception, biological sciences, elementary school, natural sciences
Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, miskonsepsi dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) telah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil Seminar Internasional. Miskonsepsi dalam IPA dan Matematika (Novak, 1987) ditemukan bahwa miskonsepsi terhadap konsep IPA banyak terjadi pada murid di berbagai negara mulai dari murid tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT). Miskonsepsi dapat terjadi di dalam dan di luar sekolah. Guru dan buku dapat menjadi sumber miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Hal ini didukung oleh penelitian Suryanto, dkk (1997) yang menunjukkan banyak guru yang mengalami miskonsepsi dan penelitian Ivowi dan Uludotun (1987) yang menemukan bahwa buku pelajaran, pengalaman sehari-hari murid, serta pengetahuan yang dimiliki guru merupakan penyebab miskonsepsi. Namun demikian, lingkungan juga dapat menjadi penyebab miskonsepsi yang terjadi di luar sekolah.Yuni Tri Hewindati tenaga pengajar pada FMIPA Universitas Terbuka Adi Suryanto adalah tenaga pengajar pada FKIP Universitas Terbuka
61
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
Adanya miskonsepsi pada murid berpengaruh terhadap prestasi IPA di sekolah. Berdasarkan tes sampling nasional tahun 1981/1982 ternyata daya serap hasil belajar IPA murid SD kurang dari 50% dan berdasarkan hasil EBTANAS tahun 1984/1985 dari 21 propinsi nilai rata-rata IPA adalah 5.39 dari nilai maksimal 10 (Jiyono, 1992). Sedangkan dari data EBTANAS 1999/2000 di 25 propinsi nilai rata-rata IPA adalah 5.96 dari nilai maksimum 10 (hhtp://www.ebtanas.org/ sd.data.asp). Penelitian yang berhubungan dengan miskonsepsi terhadap konsep IPA telah banyak dilakukan, antara lain Pembelajaran, Konsep, dan Kesalahan Konsep IPA yang Sering Dijumpai di SD (Sulistiorini, 1999); Studi Identifikasi Miskonsepsi Materi IPA Murid Kelas Enam Sekolah Dasar di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Amani, 1993); Pemahaman murid SD terhadap Konsep IPA: Suatu Diagnosis Adanya Miskonsepsi (Suryanto, 1996). Penelitian yang dilakukan ternyata lebih banyak pada penelitian tentang miskonsepsi dalam konsep IPA yang terjadi pada murid pada suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian hanya mencakup satu wilayah tertentu yang kurang dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai miskonsepsi pada murid secara lebih komprehensif. Untuk melengkapi hasil-hasil penelitian tentang miskonsepsi terhadap konsep IPA maka masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian sejenis dengan lebih memperluas lokasi penelitian. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasikan konsep dan miskonsepsi IPA berbasis biologi pada murid SD. Penelitian dilakukan di 12 SD di Jawa Barat, DI Jogja, dan Jawa Timur pada bulan Februari Maret 2001. Sampel SD dipilih dengan sengaja dengan memperhatikan prestasi pendidikan dengan meminta masukan dari penilai profesional di Dinas Pendidikan setempat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian mengacu pada pola yang dikembangkan oleh Osborne dan Cosgrove (1993) yaitu wawancara mendalam. Teknik wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pemahaman murid secara mendalam tentang konsep bernafas, bergerak, fotosintesis, dan klasifikasi hewan. Wawancara dilakukan terhadap 16 murid yang mewakili pengetahuan IPA baik, sedang, dan kurang dari tiap-tiap SD sampel. Konsep tentang suatu objek diperoleh dari hasil persepsi terhadap gejala-gejala alam, karena dari persepsi tersebut diperoleh pemahaman konseptual tentang objek tersebut. Sebagai contoh, dari hasil persepsi terhadap bermacam-macam bentuk meja akan diperoleh pemahaman konseptual tentang meja. Semakin luas pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap suatu objek, semakin berkembanglah konsep yang diperoleh tentang objek tersebut (Sund dan Trowbridge, 1973).
62
Hewindati, Pemahaman Murid Sekolah
Menurut Amien (1990) konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang didasarkan pada pengalaman tertentu yang relevan dan yang dapat digeneralisasikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu konsep akan terbentuk apabila dua atau lebih objek dapat dibedakan berdasarkan ciriciri umum, bentuk atau sifat-sifatnya. Bourne seperti dikutip oleh Amien menyatakan bahwa suatu konsep dapat dianggap sebagai suatu unit pikiran atau gagasan. Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu konsep tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem dinamik yang disebut sistem konseptual. Sebagai contoh konsep ekosistem terdiri atas konsep-konsep tumbuhan, hewan, sinar matahari, jaring-jaring makanan, siklus materi, aliran energi, dan faktor-faktor lingkungan. Cara paling objektif untuk memperoleh kebenaran suatu konsep adalah dengan menggunakan metode ilmiah (Djohar, 1993). Suatu konsep dikatakan objektif jika dapat dikonfirmasikan dengan kenyataannya, artinya simbol yang ada dalam konsep tersebut dapat ditelusuri keberadaannya di alam nyata. Oleh karena itu konsep dapat diartikan sebagai buah pikir manusia tentang alam nyata yang dinyatakan dengan simbol atau bahasa. Konsep tentang suatu objek dapat diperoleh anak sejak ia masih kecil. Konsep tersebut modifikasi atau perubahan sejalan dengan pengalaman baru yang diperoleh anak, dalam kehidupan sehari-hari. Semakin luas pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap suatu objek, semakin berkembang konsep yang diperoleh tentang objek tersebut (Sund dan Trowbridge, 1973). Menurut Ausubel seperti dikutip Dahar (1988) konsep yang dimiliki anak dapat diperoleh melalui dua cara yaitu formasi konsep (concept formation) dan asimilasi konsep (concept assimilation). Formasi konsep terutama merupakan bentuk perolehan konsep sebelum anak masuk sekolah sedangkan asimilasi konsep merupakan cara utama untuk memperoleh konsep atau belajar konsep selama dan sesudah sekolah. Sementara itu, menurut Gagne yang dikutip oleh Dahar (1988), belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme mengalami perubahan perilaku karena adanya pengalaman. Pendapat senada disampaikan oleh Woolfolk dan McCune-Nocolich (1984) yang menyatakan bahwa proses belajar telah terjadi jika di dalam diri anak telah terjadi perubahan. Perubahan dalam diri anak dikatakan sebagai hasil proses belajar jika perubahan tersebut diperoleh dari pengalaman sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Jadi belajar ditandai oleh dua faktor yaitu adanya perubahan dan pengalaman. Menurut Fisher seperti dikutip oleh Amien (1990), IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-
63
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
metode yang berdasarkan observasi. Dengan demikian dalam pembelajaran IPA diharapkan ada keterlibatan langsung antara anak dengan objek yang sedang dipelajari. Seorang anak yang mempelajari IPA akan menemukan pengertian-pengertian tentang sejumlah gejala melalui pengetahuan panca inderanya. Lebih jauh, Brody (1987) menyatakan bahwa konsep terpenting dalam pembelajaran IPA adalah pembelajaran bermakna (meaningful learning). Menurut Ausubel seperti dikutip Dahar (1988) belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa informasi yang diterima dari luar akan disimpan di dalam otak. Dengan berlangsungnya belajar akan dihasilkan perubahan dalam sel otak terutama sel yang menyimpan informasi yang mirip dengan informasi yang sedang dipelajari. Dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada subsumer yang relevan yang telah ada dalam struktur kognitif. Belajar bermakna yang baru dapat mengakibatkan pertumbuhan dan modifikasi pada subsumer relevan yang telah ada. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep atau subsumer - subsumer yang relevan yang menyebabkan tidak terjadinya proses asimilasi pengetahuan baru dengan konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif maka informasi baru tersebut akan dipelajari secara hafalan. Agar pengajaran IPA dapat memberikan hasil yang baik maka guru harus mempunyai persiapan yang matang, dan mampu memilih tujuan, isi dan metode yang tepat. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran, kemampuan dalam memilih metode dan media mengajar yang tepat akan berpengaruh terhadap efektifitas proses belajar mengajar. Hiller seperti dikutip Woolfolk dan McCune-Nicolich (1984) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas penjelasan dan pengetahuan guru dengan pencapaian belajar murid. Kurangnya pengetahuan guru akan menyebabkan tidak jelasnya penyajian pelajaran yang dapat menimbulkan miskonsepsi. Sementara itu Winkel (1991) mengemukakan bahwa penguasaan guru tentang bidang studi merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dengan dikuasainya materi pelajaran, guru tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan berbagai variasi metode mangajar. Dalam kaitannya dengan penggunaan metode mengajar, persoalannya bukan pada penting atau tidaknya metode mengajar untuk menyampaikan materi tetapi lebih pada alasan fungsional, yaitu bagaimana guru dapat memilih metode yang dapat berfungsi secara maksimal untuk mendorong aktivitas belajar murid (Zuchdi dan Soeninggjo, 1982). Lebih lanjut dikatakan bahwa metode apapun yang akan digunakan, guru harus dapat menciptakan aktivitas belajar yang
64
Hewindati, Pemahaman Murid Sekolah
sebagian besar dilakukan murid. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar guru harus menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jika dalam proses belajar mengajar diciptakan iklim yang positif maka guru akan dapat mengajar dengan lebih baik dan murid akan belajar lebih banyak (Hayman, 1980). Bruner seperti dikutip lvowi dan Oludotun (1987) berpendapat bahwa murid akan siap belajar apabila guru siap untuk mengajar, dan keefektifan guru dalam mengajar merupakan faktor penting untuk pembentukkan konsep pada murid. Jika murid memiliki pemahaman tentang suatu konsep yang berbeda dengan konsep guru atau konsep ilmuwan maka untuk menghilangkan perbedaan tersebut, dalam proses belajar mengajar dapat dibuat variasi aktivitas pembelajaran sebagai berikut (Oborne dan Wittrock, 1983): 1. Mengadakan wawancara dengan murid serta menghargai pendapat mereka dan mengembangkan keterampilan bertanya dan mendengarkan. 2. Mengadakan diskusi kelompok untuk menjernihkan perbedaan ide-ide murid dengan ide ilmuwan. 3. Merancang percobaan untuk menguji dugaan-dugaan yang mengikuti ide murid. 4. Mempelajari bukti-bukti studi kritik untuk penyusunan kembali pengetahuan ilmiah. 5. Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan alasan mengapa murid tetap memegang teguh pandangan khusus atau mempunyai arti khusus tentang sesuatu yang berbeda dengan ide ilmuwan. Jika beberapa potong es batu dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang kering maka setelah beberapa saat kemudian akan ditemukan titik air yang menempel di permukaan luar gelas. Menurut para ilmuwan munculnya titik air yang menempel di permukaan gelas tersebut berasal dari uap air berada di udara sekitar gelas. Pada saat udara yang mengandung air tersebut menyentuh permukaan gelas yang dingin maka uap air akan mengembun dan menempel pada permukaan gelas. Jika situasi percobaan tersebut dihadapkan kepada murid mungkin akan ditemukan beberapa murid yang mempunyai pemahaman yang berbeda satu sama lain tentang konsep mengembun tersebut. Pemahaman setiap murid terhadap suatu konsep inilah yang disebut dengan konsepsi (Van den Berg, 1991). Lebih lanjut dikatakan bahwa konsepsi murid terhadap suatu konsep dapat benar atau salah. Jika konsepsi murid terhadap suatu konsep sama dengan konsepsi para ilmuwan, dikatakan murid tersebut mempunyai konsepsi yang benar. Jika konsepsi murid tentang suatu konsep berbeda dengan konsepsi para ilmuwan, dikatakan murid tersebut mengalami miskonsepsi. Biasanya miskonsepsi terjadi pada kesalahan dalam pemahaman hubungan antar konsep.65
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
Fowler dan Jaoude (1987) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan miskonsepsi adalah pengertian tentang suatu konsep yang tidak tepat, salah dalam menggunakan konsep nama, salah dalam mengklasifikasikan contoh-contoh konsep, keraguan terhadap konsepkonsep yang berbeda, tidak tepat dalam menghubungkan berbagai macam konsep dalam susunan hierarkinya atau pembuatan generalisasi suatu konsep yang berlebihan atau kurang jelas. Menurut Amien (1990) miskonsepsi dapat pula terjadi karena adanya gagasan atau ide yang didasarkan pada pengalaman yang tidak relevan. Beberapa contoh miskonsepsi dalam IPA antara lain: Katak tergolong dalam reptilia, bumi berputar mengelilingi matahari dan bumi beredar pada porosnya, vertebrata adalah salah satu dari mamalia, massa sama dengan berat, anjing laut merupakan salah satu jenis ikan dan sebagainya. Jika miskonsepsi terjadi pada murid, miskonsepsi tersebut cenderung menetap dan sulit untuk diubah serta akan berpengaruh pada proses belajar mengajar berikutnya (Amir dan Tamir, 1987). Miskonsepsi yang dialami oleh murid dapat terjadi di sekolah atau di luar sekolah. Menurut Osborne, Bell dan Gilbert seperti dikutip Osborne dan Wittrock (1983), faktor-faktor yang potensial menjadi sumber miskonsepsi adalah: 1. Anak cenderung melihat suatu benda dari pandangan dirinya sendiri dan cenderung untuk menentukan keberadaan dan bentuk benda tersebut hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari. 2. Pengalaman anak di lingkungan terbatas dan cenderung tidak terlibat langsung dalam situasi percobaan. 3. Untuk kejadian-kejadian khusus anak cenderung diarahkan pada penjelasan bagian per bagian dan cenderung tidak diarahkan untuk memahami hubungan satu dengan yang lain secara keseluruhan serta adanya penjelasan yang sama untuk menjelaskan fenomena yang berbeda. 4. Bahasa yang digunakan sehari-hari cenderung berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam IPA, misalnya kata berat, gesekan, dan gaya di mana arti dalam bahasa sehari-hari cenderung berbeda. Russell seperti dikutip oleh Vaidya (1976) menyatakan bahwa penyebab miskonsepsi pada anak antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam mempersepsi konsep yang muncul, kerancuan antara kesan dan memori yang sudah ada dalam otak selama mengingat, tidak mengecek kebenaran dari generalisasi yang diperoleh atau terlalu yakin terhadap hasil salah satu observasi dan pemikiran konseptual.
66
Hewindati, Pemahaman Murid Sekolah
HASIL DAN PEMBAHASANTabel 1: Pemahaman murid SD terhadap pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Respon murid Menghirup udara dan mengeluarkan CO2 Menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara kotor Menghirup dan mengeluarkan udara Tidak tahu Total Frekuensi 145 20 4 17 186 Persentase 78 10,8 2 9,2 100
Tabel 2: Pemahaman murid terhadap pertanyaan: Apakah tumbuhan juga bernapas? jika ya, kapan? Respon murid Ya, setiap saat Ya, pada siang hari Ya, pada malam hari Tidak bernapas Total Frekuensi 110 41 30 5 186 Persentase 59,1 22 16,3 2,6 100
Tabel 3: Pemahaman murid terhadap pertanyaan: Apakah tumbuhan dapat bergerak? Respon murid Ya, dapat tumbuh tinggi, akar memanjang, gerakan putri malu Ya, saat tertiup angin Tidak Tidak tahu Total Frekuensi 61 77 42 6 186 Persentase 32,8 41,4 22,6 3,2 100
Tabel 4: Pemahaman murid terhadap pertanyaan: Kapan proses fotosintesis terjadi? Respon murid Siang hari saat ada cahaya matahari Malam hari Siang dan malam asal ada cahaya Tidak tahu Total Frekuensi 128 7 48 3 186 Persentase 68,8 3,7 25,8 1,7 10067
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
Tabel 5: Pemahaman murid terhadap pertanyaan: Termasuk dalam kelompok apakah Kelelawar, Ikan lumba-lumba, Buaya, dan Ikan Hiu? a. Kelelawar Respon murid Burung, karena punya sayap dan dapat terbang Mamalia karena menyusui Tidak tahu Total b. Ikan lumba-lumba Respon murid Ikan karena hidup di air dan bentuknya seperti ikan Mamalia karena menyusui Tidak tahu Total c. Buaya Respon murid Reptil karena melata Amphibi karena hidup di dua tempat Ikan karena hidup di air Tidak tahu Total Frekuensi 123 40 10 13 186 Persentase 66,1 21,5 5,4 7 100 Frekuensi 88 65 33 186 Frekuensi 78 79 29 186 Persentase 47,3 34,9 17,8 100 Persentase 41,9 42,5 15,6 100
d. Ikan Hiu Respon murid Ikan karena hidup di air Mamalia karena menyusui Tidak tahu Total
Frekuensi 102 70 14 186
Persentase 54,8 37,6 7,6 100
Jika digunakan standar 75 % sebagai batas tingkat penguasaan konsep yang baik maka hanya terdapat satu konsep yang dapat dipahami dengan baik oleh murid SD yaitu konsep bernapas (78 %), dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Hasil penelitian
68
Hewindati, Pemahaman Murid Sekolah
menunjukkan miskonsepsi yang dialami murid cukup banyak, misalnya tumbuhan hanya bernapas pada malam hari (Tabel 2), tumbuhan tidak bergerak (Tabel 3), tumbuhan dapat bergerak jika tertiup angin (Tabel 3), fotosintesis hanya terjadi pada siang hari (Tabel 4), Kelelawar termasuk dalam kelompok burung (Tabel 5a), dan Lumba-lumba termasuk dalam kelompok ikan (Tabel 5b). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (1996), Joychareon (1986), Mintzes dan Trowbridge (1987). Berdasarkan hasil analisis terhadap pola jawaban yang diberikan murid pada saat wawancara, ditemukan beberapa miskonsepsi yang disebabkan karena dalam menjelaskan sesuatu konsep murid memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman sehari-hari misalnya tumbuhan tidak bergerak (22,6 %), tumbuhan bergerak jika tertiup angin (41,4 %), kelelawar termasuk kelompok burung (47,3 %), dan lumbalumba termasuk kelompok ikan (41,9 %). Berdasarkan pengalaman sehari-hari yang dilihat oleh murid, suatu benda dikatakan bergerak jika keseluruhan atau sebagian benda tersebut dapat bergerak berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berdasarkan pengalaman sehari-hari pula murid melihat bahwa hewan yang dapat terbang adalah hewan yang mempunyai sayap dan hewan yang demikian termasuk kelompok burung. Pengalaman sehari-hari yang lain juga menunjukkan bahwa hewan yang hidup di air dan bentuknya seperti ikan adalah kelompok ikan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Osborne, Bell, dan Gilbert seperti dikutip oleh Osborne dan Wittrock (1983) yang menyatakan bahwa miskonsepsi yang terjadi pada seseorang antara lain disebabkan karena ia cenderung melihat suatu benda dari pandangan dirinya sendiri dan cenderung untuk menentukan keberadaan dan bentuk suatu benda tersebut berdasarkan pengalaman sehari-hari. Lebih lanjut dikatakan bahwa miskonsepsi dapat pula disebabkan karena dalam memahami suatu konsep anak tidak dilibatkan langsung dalam situasi percobaan. Hal ini terlihat pada miskonsepsi murid dalam memahami bernapas (Tabel 2) dan konsep fotosintesis (Tabel 4). Pada kenyataannya masih banyak ditemukan proses pembelajaran IPA yang terjadi di lapangan dilakukan tanpa melibatkan langsung siswa dengan situasi percobaan. Pembelajaran IPA hanya dilakukan dengan metode ceramah. Secara teoritis miskonsepsi yang terjadi pada murid juga dapat disebabkan karena adanya miskonsepsi pada guru dan atau buku. Suryanto (1997) menemukan banyak guru SD yang mengalami miskonsepsi dalam IPA dan Ivowi dan Uludotun (1987) menemukan bahwa buku yang digunakan untuk mengajar, pengalaman murid seharihari, dan pengetahuan yang dimiliki guru merupakan penyebab miskonsepsi.
69
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
KESIMPULAN DAN SARAN Kesalahan konsepsi masih banyak ditemukan. Hal ini terbukti dari sedikitnya konsep yang dapat dipahami dengan benar oleh murid. Jika dipakai angka 75% pemahaman konsep yang benar maka hanya terdapat satu konsep yang dapat dipahami dengan baik oleh murid yaitu konsep tentang bernapas. Berdasarkan analisis terhadap pola jawaban yang diberikan murid ditemukan bahwa kesalahan konsepsi yang terjadi pada murid lebih banyak disebabkan karena dalam memahami suatu konsep, murid memberikan jawaban berdasarkan pada pengalaman yang mereka lihat sehari-hari. Sejalan dengan temuan dan analisis disarankan agar pada saat mengajarkan konsep tentang gerak pada tumbuhan sebaiknya guru mengajak murid untuk melakukan percobaan sederhana yang dapat menunjukkan dengan jelas bahwa tumbuhan juga melakukan gerak. Temuan bahwa pemahaman murid tentang konsep pengelompokkan hewan yang masih sangat kacau perlu ditindak-lanjuti guru pada saat mengajarkan konsep tersebut dengan melibatkan secara langsung murid dalam diskusi dan memberikan dasar klasifikasi yang lengkap dan tidak sepotong sepotong. Disamping itu, perlu dilakukan analisis isi terhadap buku teks yang digunakan di sekolah, khususnya yang menyangkut konsep fotosintesis. Hal ini perlu dilakukan mengingat dari hasil penelitian ini ditemukan kesalahan konsepsi yang cukup besar pada murid saat ditanya tentang kapan proses fotosintesis terjadi. DAFTAR RUJUKAN Amien, M. (1990). Pemetaan konsep: Suatu tehnik untuk meningkatkan belajar yang bermakna. Mimbar Pendidikan. 2. Tahun IX, 55-69. Amir, D. R. & Tamir, F.P. (1987). Justifications of answers to multiple choice items as a means for identifying misconceptions. Dalam Novak, J.D. (Ed). Proceeding of the second international seminar misconcepsition and educational strategies in Science and Mathematics. 1. Ithaca, New York: Cornell University. Brody, M. J. (1987). A programmatic approach to teaching and learning about student understanding of science and natural resource concepts related to environmental issues. Dalam Novak, J.D. (Ed). Proceeding of the second international seminar misconcepsition and educational strategies in Science and Mathematics. 1. Ithaca, New York: Cornell University. Dahar, R. W. (1988). Teori-teori belajar. Jakarta: Proyek Pembangunan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
70
Hewindati, Pemahaman Murid Sekolah
Djohar. (1993). Analisis hubungan antara konsep dengan unsur-unsur penyusunannya sebagai pendekatan untuk deskripsi kesulitan memahami konsep dan proses konseptualisasi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (Sains). Laporan penelitian. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: FPMIPA IKIP Yogyakarta. Fowler, T. W. & Jaoude, S. B. (1987). Using hierarchichal concept/proposition maps to plan instruction that addresses existing and potential student misunderstanding in science. Dalam Novak, J.D. (Ed). Proceeding of the second international seminar misconcepsition and educational strategies in Science and Mathematics. 1. Ithaca, New York: Cornell University. http://www.ebtanas.org/sd./data.asp Hayman, R. T. (1980). School administrators handbooks of teacher supervision and evaluation methods. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Jiyono. (1992). Kemampuan/pemahaman guru tentang IPA dan sarana pelajaran IPA di Sekolah Dasar. Laporan penelitian. Jakarta: Balitbang Dikbud. Joychareon, K. (1986). An investigation of Thai secondary students understanding of concept related to animals. Laporan penelitian. Tidak diterbitkan. Penang: SEAMEO-RECSAM. Ivomi, U. M. O. & Oludotun, J. S. O. (1987). An investigation of resources of misconception in physics. Dalam Novak, J.D. (Ed). Proceeding of the second international seminar misconcepsition and educational strategies in Science and Mathematics. 3. Ithaca, New York: Cornell University. Novak, J. D. (Ed.) (1987). Proceeding of the second international seminar misconcepsition and educational strategies in Science and Mathematics. 1, 2, 3. Ithaca, New York: Cornell University Osborne, R. J., & Wittrock, M. (1983). Learning science: A generative process. Science education. 67(4): 489-508. Suryanto, A. (1996). Pemahaman murid Sekolah Dasar (SD) terhadap konsep-konsep Ilmu Pengetahuan Alam (IPA): Suatu diagnosis adanya miskonsepsi. Tesis. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPS IKIP Yogyakarta. Suryanto, A., dkk (1997). Pemahaman guru Sekolah Dasar (SD) terhadap Konsep konsep Ilmu Pengetahuan Alam (IPA): Suatu diagnosis adanya miskonsepsi. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan. Jakarta: Pusat Penelitian-UT. Sulistiorini (1999). Pembelajaran, konsep, dan kesalahan konsep IPA yang sering dijumpai di Sekolah Dasar. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan. Jakarta: Pusat Penelitian-UT.
71
Jurnal Pendidikan, Vol.5, No. 1, Maret 2004, 61-72
Sund, R. B., dan Trowbridge, L. M. (1973). Teaching Science by inquiry in the secondary school 2nd ed. Columbia, Ohio: Charles E. Merril Publishing Company. Vaidya, N. (1976). The impact science teaching. New Delhi: Oxford & IBH Pub.Co. Van den Berg, E. (Ed). (1991). Miskonsepsi fisika dan remidiasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
Winkel, W. S. (1991). Psikologi pengajaran. Jakarta: PT Grasindo.Wollfolk, A. E., & McCune-Nicolich, L. (1984). Educational psychology for teachers. 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Inc. Zuchdi dan Soeninggjo. (1982). Penilaian bidang studi IPA pada SD tahun 1980/1981. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan. Jakarta: Balitbang Dikbud.
72